Serba-Serbi Ir. Soekarno (Presiden Sepanjang
Masa RI)
Pengalaman Pertama Bung Karno Naik Kuda
Tahun 1946, setahun setelah proklamasi, masih banyak hal-hal aneh, unik, lucu, dan menggelikan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, rakyat belum mengerti benar arti merdeka. Mereka ada yang mengartikan, merdeka adalah bebas naik kereta api. Jad, manakala kondektur memungut ongkos, mereka tersinggung, “Lho,” teriak rakyat, “kan kita sudah merdeka?”

Terhadap Bung Karno? Tak seorang pun memanggil Tuan Presiden, apalagi Paduka Yang Mulia sebagai sebutan formal. Mereka tetap saja menyebut “Presiden Bung Karno”, gabungan dari jabatan resmi dan panggilan akrab sehari-hari. Begitu Bung Karno menceritakan situasi awal-awal kemerdekaan kepada penulis biografinya, Cindy Adams.

Tahun 1946, setahun setelah proklamasi, masih banyak hal-hal aneh, unik, lucu, dan menggelikan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, rakyat belum mengerti benar arti merdeka. Mereka ada yang mengartikan, merdeka adalah bebas naik kereta api. Jad, manakala kondektur memungut ongkos, mereka tersinggung, “Lho,” teriak rakyat, “kan kita sudah merdeka?”
Terhadap Bung Karno? Tak seorang pun memanggil Tuan Presiden, apalagi Paduka Yang Mulia sebagai sebutan formal. Mereka tetap saja menyebut “Presiden Bung Karno”, gabungan dari jabatan resmi dan panggilan akrab sehari-hari. Begitu Bung Karno menceritakan situasi awal-awal kemerdekaan kepada penulis biografinya, Cindy Adams.
Kejadian menarik juga menimpa Bung Karno ketika tanggal 5 Oktober 1946, Angkatan Perang kita (sekarang TNI) hendak merayakan ulang tahun yang pertama. Dalam salah satu tata cara upacara militer yang sudah direncanakan semegah-megahnya untuk ukuran negara berusia satu tahun, Presiden Republik Indonesia Sukarno, harus melakukan inspeksi pasukan… naik kuda!
Persoalannya adalah… Bung Karno tidak pernah naik kuda. Pergaulan Bung Karno dengan seekor kuda pada masa-masa sebelumnya, tak lebih dari sekadar menepuk-nepuk kuduknya. Demi mengetahui hal itu, Fatmawati, istrinya, ikut cemas. “Jadi, bagaimana caranya,” tanya Fatma. Bung Karno menjawab, “Pertama, aku hendak menghadapi kenyataan bahwa aku orang yang pelagak… Aku akan belajar naik kuda!”
Fatma belum hilang rasa cemasnya, “Kan pawainya besok?” Lalu Bung Karno menjawab, “Ya, aku akan belajar dalam satu hari.”
Akhirnya, seorang perwira kavaleri tekun memberikan pelajaran berkuda kepada presidennya. Dan di akhir sesi latihan, kepada si perwira kavaleri itu, Bung Karno menyampaikan pesan dengan suara pelan… “Untuk pawai besok, berilah saya kuda yang paling lunak, paling tua, paling jinak dan hampir mendekati kematiannya….”
Tak bisa dimungkiri, Bung Karno sebenarnya memendam rasa cemas dan khawatir. Apa jadinya kalau dalam pawai inspeksi pasukan besok si kuda menjadi beringas dan tak terkendali? Bagaimana kalau ia kemudian terpental dari punggung kuda? Apa kata dunia?
Dan… perwira kavaleri itu menjawab, “Tidak Pak. Tidak pantas untuk Bapak. Kuda yang disediakan harus yang muda dan garang. Dia harus memperlihatkan semangat tempur yang menyala-nyala, dan kuda yang terbaik dari seluruh kelompok.”
Bung Karno yang pelagak, tak berkutik dengan jawaban perwira kavaleri. Rasa cemas ia pendam dalam hati…. hingga, tibalah saat-saat yang dinanti. Terompet telah berbunyi, genderang berderam-deram, pasukan berdiri tegap, dan… Presiden menaiki kudanya. Binatang itu berjalan mengikuti irama musik… dan… menjadi liar. Bung Karno sedikit ciut, tapi ketika ia melihat pasukan yang berbaris rapi yang sedang ia inspeksi… muncullah sifat pelagaknya… Sorak-sorai dan teriakan gembira dari rakyat yang berjejal-jejal di lapangan pawai menghidupkan semangat.
Suasana itu membuat Bung Karno tenang dan sadar… hilang rasa cemas, dan muncul teori-teori berkuda yang telah diajarkan si perwira kavaleri kemarin. Maka, dengan sigap Bung Karno segera memainkan pegelangan, menguasai tunggangannya dengan baik. Bung Karno mengendalikan langkah kuda dengan begitu gagah, sehingga kuda berjalan dengan langkah tenang dan teratur seperti yang dikehendaki. Dan… kuda yang bagus itu tidak pernah menyadari bahwa tuannya lebih gentar menghadapi peristiwa itu daripada binatang itu sendiri. (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Cara Pandang Bung Karno tentang Pakaian



Rasanya untuk statemen yang satu ini, saya harus gambling… sebab memang belum ada satu rujukan pun yang pernah saya jumpai terkait hal yang jadi bahasan posting-an ini. Ini soal cara Bung Karno berpakaian. Bahwa sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga maut menjemput, belum pernah sekali pun Bung Karno mengenakan pakaian daerah. Sekali lagi, ini statemen spekulatif. Karenanya, saya harus berani mempertaruhkan kredibilitas.
Satu-satunya rujukan yang pernah saya baca hanyalah keterangan Bambang Widjanarko, ajudan Bung Karno. Katanya, selama delapan tahun menjadi ajudan Bung Karno, belum pernah sekalipun ia melihat Bung Karno mengenakan pakaian adat. Hal ini tentu saja mendatangkan pertanyaan banyak pihak, termasuk Bambang. Karenanya, pada saat santai di tahun 1964, Bambang melihat satu kesempatan yang baik untuk menanyakan hal itu. Dan,.. Bung Karno pun memberi penjelasan….
“Sejak dulu sampai sekarang dan untuk seterusnya, yang amat aku dambakan adalah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Karena aku ditakdirkan menjadi pemimpin, dan sekarang menjadi Presiden Indonesia, aku harus mengorbankan kesukuan Jawa-ku, untuk membuktikan kesungguhan keindonesiaanku itu. Baik resmi atau tidak resmi, siang maupun malam, aku ini tetap Presiden Indonesia, bukan presidennya orang Jawa saja. Selama aku jadi Presiden, seluruh mata bangsa Indonesia akan melihat dan memperhatikanku, termasuk pakaian yang aku pakai. Itu sebabnya aku selalu berpakaian rapi dan memakai peci hitam, yang aku harapkan menjadi ciri atau identitas bangsa Indonesia.”

Terhadap pakaian daerah, begini penuturan Bung Karno, “Aku sama sekali tidak anti pakaian adat daerah, bahkan sebaliknya aku pengagum atau penganjur dilestarikannya pakaian adat itu. Hanya bagi pejabat tinggi negara, sebaiknya ada batas-batasnya. Contoh, Gubernur Aceh berpakaian adat Aceh atau Gubernur Bali berpakaian adat Bali, itu baik sekali; mereka itu memang kepala dari daerah yang dipimpinnya. Sedangkan untuk presiden atau menteri, seyogianya tidak berpakaian daerah, karena mereka adalah pemimpin seluruh Indonesia. Nanti bila ia tidak menjabat lagi, barulah bebas dan boleh berpakaian apa saja yang ia senangi.”
Itulah pendapat Bung Karno tentang pakaian adat. Tidak heran, kalau Bung Karno begitu dicintai seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Cinta rakyat yang tulus… sebagai balasan atas ketulusan Sukarno yang rela melepas segala atribut kedaerahan, kepartaian, dan kepentingan pribadinya untuk bangsa dan negara yang begitu dicintainya: INDONESIA. (roso daras)
Itulah pendapat Bung Karno tentang pakaian adat. Tidak heran, kalau Bung Karno begitu dicintai seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Cinta rakyat yang tulus… sebagai balasan atas ketulusan Sukarno yang rela melepas segala atribut kedaerahan, kepartaian, dan kepentingan pribadinya untuk bangsa dan negara yang begitu dicintainya: INDONESIA. (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
“Pating Greges,” kata Bung Karno di Pagi 17 Agustus 1945






Tidak seperti hari-hari sebelumnya, pagi hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, langit di atas kota Jakarta biru cerah. Suasana di kediaman Bung Karno, Jl Pegangsaan Tmur 56, Menteng, Jakarta Pusat sudah ramai. Di halaman depan, di ruang pendapa, hingga di halaman belakang, dipadati para patriot dengan raut antusias, menyongsong detik-detik yang menentukan nasib bangsa ke depan.

Sementara itu, Bung Karno sendiri masih lelap. Maklum, ia baru masuk kamar menjelang shubuh, setelah semalam padat aktivitas menjelang proklamasi kemerdekaan. Di antaranya, rapat intensif di kediaman Laksamana Maeda, tokoh militer Jepang yang disebut-sebut menjanjikan bantuan bagi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jam dinding menunjuk angka 8 ketika dr R. Soeharto, dokter pribadi Bung Karno, menyelinap masuk ke kamar Bung Karno. Ia memandang Putra Sang Fajar masih pulas. Didekatinya tempat tidur Bung Karno, dan diusapnya tangan Bung Karno… mata pun terbuka. Sorot kelelahan memancar dari kedua bola mata Bung Karno. Kalimat pertama di pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 yang keluar dari mulut Bung Karno kepada dr. R. Soeharto adalah, “Pating greges”.

Ungkapan dalam bahasa Jawa yang bisa diartikan sebagai “kondisi badan yang pegal-linu karena gelaja demam.” Apalagi, ketika dr Soeharto meraba badan Bung Karno, panas. Sebagai dokter pribadinya, dia langsung melakukan pemeriksaan, dan atas persetujuan Bung Karno, dr Soeharto memberinya suntikan chinine-urethan intramusculair, dan meminta Bung Karno meminum broom chinine.
Setelah disuntik dan minum obat, tak lama kemudian Bung Karno tertidur lagi. Dr Soeharto keluar kamar, dan berpapasan dengan Fatmawati. Kepada Bu Fat, dijelaskan ihwal sakitnya Bung Karno. Bu Fat sempat berujar, “Saya sendiri sebetulnya juga capek sekali setelah kembali dari Rengasdengklok dan menyelesaikan pembuatan bendera yang akan dikibarkan hari ini.”

Detik demi detik bergulir…. waktu menunjuk pukul 09.30 ketika dr Soeharto melihat Bung Karno terbangun dengan kondisi badan yang lebih sehat. Panasnya sudah reda. Ia segera beranjak dari tempat tidur demi mendengar kata-kata Soeharto, “sudah jam setengah sepuluh mas…”. Setelah itu, Bung Karno berkata, “Minta Hatta segera datang.”
Selagi dr Soeharto meneruskan perintah Bung Karno kepada Latief Hendraningrat, Bung Karno mempersiapkan diri demi momentum paling bersejarah bagi bangsa kita. Ia berpakaian rapi, mengenakan busana serba putih: celana lena putih dan kemeja putih dengan potongan yang populer disebut “kemeja pimpinan”. Lengannya panjang, bersaku empat, dengan band pinggang di belakang. Ia begitu gagah, penuh percaya diri.
Sebelum membacakan teks proklamasi, Bung Karno memberi kata pengantar dengan intonasi yang begitu gamblang, dan suara yang tenang:

Saudara-saudara sekalian
Saya telah minta Saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan Tanah Air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita.
Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendir.
Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib Tanah Air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusyawaratanitu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.
Saudara-saudara! Dengan ini kami nyatakan kebupatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami:
Saya telah minta Saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan Tanah Air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita.
Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendir.
Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib Tanah Air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusyawaratanitu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.
Saudara-saudara! Dengan ini kami nyatakan kebupatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami:
Dan… Bung Karno pun membacakan teks proklamasi dengah khidmat.
Begitulah sekelumit kisah, beberapa saat sebelum detik-detik bersejarah, berlangsungnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. (roso daras)
Begitulah sekelumit kisah, beberapa saat sebelum detik-detik bersejarah, berlangsungnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Cinta Carlos kepada Bung Karno




Tahukah Anda, Bung Karno memiliki sopir khusus seorang warga Roma, Italia bernama Carlos. Bung Karno begitu menyayangi dia, begitu pula sebaliknya. Ihwal kedekatan Bung Karno dengan para sopir atau bawahan lain pada umumnya, tak lain karena Bung Karno begitu perhatian kepada hal-hal kecil. Seperti misalnya setiap kunjungan ke daerah-daerah, dari satu tempat ke tempat lain, Bung Karno akan selalu dan berkali-kali menanyakan “status kesejahteraan” sopir. Harus cukup istirahatnya. Harus cukup makannya. Harus tenang hatinya. “Keselamatan kita di tangannya,” ujar Bung Karno suatu hari kepada ajudan Bambang Widjanarko.

Perhatian khusus itu pula yang merebut hati bawahan, sehingga mereka benar-benar mencintai Bung Karno. Tak terkecuali seorang sopir berkebangsaan Italia. Carlos, si sopir itu, adalah langganan Kedutaan RI setempat setiap kali Bung Karno berkunjung ke sana. Dan ketika pada suatu hari Bung Karno berkunjung ke Roma, dan si sopir bukanlah Carlos, serta-merta Bung Karno bertanya kepada Dubes, “Mengapa sopirnya lain? Ke mana Carlos?”
Ketika dicek ke perusahaan tempat Carlos bekerja, diketahui Carlos sedang berlibur ke Swiss atas tanggungan perusahaan. Maka, Bung Karno pun segera bertitah, “Panggil dia pulang, saya mau Carlos!” Perintah pun segara dilaksanakan, dan kesokan paginya, Carlos sudah muncul di hotel, menghadap Bung Karno, memberi hormat ala militer dan berkata, “Your excellency, I am at your service.” Bung Karno menyambut gembira, “Well Carlos, where have you been? I missed you. Bagaimana kabar istri dan anak-anakmu?”
Disapa begitu, Carlos pun bercerita: “Mungkin Paduka Yang Mulia sudah mendengar ceritanya. Saya dipaksa cuti ke Swiss beserta keluarga. Memang senang bepergian ke luar negeri, apalagi dibiayai perusahaan. Tapi kemarin sore waktu kami mendapat berita dari perusahaan agar kami segera pulang karena saya harus melayani Paduka Yang Mulia, kami menjadi lebih gembira lagi. Bahkan istri saya mendesak agar kami cepat-cepat kembali ke Roma. Dan, inilah saya… siap melayani Paduka Yang Mulia.”
Bung Karno bukanlah pribadi yang egois. Demi menjaga peraaan para sopir, teman-teman sekantor Carlos, maka Bung Karno mengundang mereka makan bersama. Carlos datang bersama 10temannya. Dari event itu diketahui, bahwa kepergian Carlos berlibur ke luar negeri, mulanya karena usulan teman-temannya yang “iri”, dan ingin juga melayani Bung Karno. Maka, ketika terbetik berita Bung Karno hendak berkunjung ke Roma, diaturlah agar Carlos pergi, sehingga sopir lain berkesempatan melayani Bung Karno.
Nah, kembali ke jamuan makan malam terakhir, sebelum Bung Karno dan rombongan kembali ke Tanah Air. Usai makan spaghetti dan minum anggur dalam suasana pesta kecil, keesokan harinya, para sopir sudah berada di hotel, bersiap dengan mobil masing-masing hendak mengantar rombongan Bung Karno ke bandara. Pagi yang cerah, ketika Bung Karno keluar dari hotel hendak menuju mobil, dilihatnya para sopir berjejer di samping pintu sambil memegangi topi. Lalu, terdengar aba-aba: One – two – three ! dan terdengarlah suara para pengemudi itu bernyanyi:
“Bung Karno siapa yang punya”
“Bung Karno siapa yang punya”
“Bung Karno siapa yang punya”
“Yang punya kita semua….”
“Bung Karno siapa yang punya”
“Bung Karno siapa yang punya”
“Yang punya kita semua….”

Bung Karno tersenyum menahan haru. Para pengemudi berkebangsaan Itali menyanyikan lagi yang amat populer ketika itu, dalam bahasa Indonesia yang baik. Belakangan diketahui, para sopir itu sudah belajar dari salah seorang staf kedutaan Indonesia, dan mereka sangat menyenangi lagu tersebut.
Bung Karno mengucap terima kasih, lantas menyalami semua pengemudi satu per satu.
Bung Karno mengucap terima kasih, lantas menyalami semua pengemudi satu per satu.
Bung Karno, telah merebut hati semua pengemudi di Roma…. (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Gaya Makan Bung Karno



Tahukah Anda… Bung Karno punya style makan yang unik dan menarik…. Di kalangan para sahabatnya, Bung Karno dikenal sebagai ‘fast eater”…. “Beliau kalau makan cepat sekali selesai,” ujar Dr. R. Soeharto, dokter pribadi Bung Karno.
Pada dasarnya, Bung Karno menyukai banyak jenis makanan. Tapi yang paling dia gemari adalah sayur bening (bayam, jagung) ala Jawa yang terasa agak manis. Nasinya harus pulen. Lauknya, ayam bakar.
Usut punya usut, kebiasaan makan cepat ternyata dimulai sejak dia “langganan” masuk-keluar penjara. Jika dikalkulasi, sejak zaman pra kemerdekaan, Bung Karno mendekam di balik jeruji besi selama 12 tahun. Tentu saja tidak terus menerus. Seperti disebut di atas, ia masuk-keluar penjara. Tuduhan kepadanya umumnya subversi terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Nah, di dalam penjara, jatah waktu untuk makan (dan minum) tidak pernah lebih dari lima menit. Rata-rata jatah makan tiga menit, untuk minum 1 menit. Bahkan untuk penjaga yang ketat, tiga menit harus selesai. Karenanya, jika makannya harus dengan teor mengunyah 33 kali…. waktu habis baru dapat beberapa suap.
Kebiasaan makan cepat itulah yang kemudian terbawa oleh Bung Karno, meski ia sudah berstatus Presiden Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi, Panglima Besar Angkatan Perang. (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Cinta Bung Karno di Bumi Ende


Ini adalah sepenggal kisah di tahun 1934, ketika Bung Karno dibuang penjajah Belanda ke bumi Ende. Akan tetapi, bukan kisah cinta dalam arti asmara antara Bung Karno dengan seorang gadis. Ini adalah sepenggal rasa cinta yang disemai Bung Karno kepada rakyat Ende, sehingga “Orang Jawa” –begitu Bung Karno disebut masyarakat lokal– bisa segera mendapat balasan cinta rakyat setempat.
Ada begitu banyak nama yang melekat di hati Sukarno. Mereka terdiri atas para pembantu, para pemain sandiwara (tonil) Kelimutu yang didirikan Bung Karno… bahkan rakyat di luar pulau Ende, seperti Pulau Sabu, tempat seorang lelaki bernama Riwu Ga dilahirkan. Bung Karno memanggil Riwu Ga dengan panggilan pendek, “Wo”.
Ada begitu banyak nama yang melekat di hati Sukarno. Mereka terdiri atas para pembantu, para pemain sandiwara (tonil) Kelimutu yang didirikan Bung Karno… bahkan rakyat di luar pulau Ende, seperti Pulau Sabu, tempat seorang lelaki bernama Riwu Ga dilahirkan. Bung Karno memanggil Riwu Ga dengan panggilan pendek, “Wo”.
Dalam buku karya Peter A. Rohi, “Kako Lami Angalai?” Riwu Ga mengisahkan awal mula perkenalannya dengan Bung Karno. Dikisahkan, Riwu adalah penjaja kue keliling, hingga di suatu senja tatkala ia melintas di kediaman “keluarga Jawa”, terdengar suara perempuan memanggil, “Kue… kue…” Riwu berhenti, menoleh, tampaklah gadis kecil berkulit kuning bersih, yang belakangan Riwu kenal bernama Ratna Juami, anak angkat pasangan Bung Karno – Inggit Garnasih, yang biasa dipanggil “Omi”.
Sejurus kemudian, keluar perempuan cantik… dialah Inggit. Keduanya membeli dua potong pisang goreng yang dijajakan Riwu. Belum habis pisang dimakan, Inggit menatap tajam ke arah Ribu dan berkata, “Maukah anak bekerja dengan kami? Maukah anak tinggal dengan kami?”
Riwu muda (usianya baru 16 tahun), sangat kaget demi mendapat tawaran itu. Belum hilang rasa kaget yang tampak dari ekspresi muka terkejut Riwu, Ibu Inggit bertanya lagi, “Anak mau tinggal bersama kami? Kalau mau, anak akan dapat satu rupiah sebulan.”
Itu gaji yang besar, pikir Riwu. Bayangkan, harga satu kilogram beras waktu itu hanya dua sen. Sedangkan gajinya, ekuivalen 100 sen. Tanpa sadar, benar-benar di luar kesadarannya, Riwu mengangguk. Tapi ketika ia sadar, ia mengangguk lebih dalam. Meski begitu, bukan angka 1 rupiah yang mendorongnya menyetujui tawaran Inggit, tapi lebih didorong rasa bangga bisa bekerja pada keluarga “orang Jawa” yang sangat berwibawa itu.
Riwu segera berlari pulang, membawa sisa jajanan kue yang belum habis terjual. Ia minta izin Gadi Walu, kakak sepupu yang membawanya dari Pulau Sabu ke Ende. Ternyata, ia mendapat restu. Bukan hanya restu Gadi Walu, tetapi restu keluarga besar. Mereka bangga Riwu dipercaya menjadi pembantu di keluarga Bung Karno yang dikenal sebagai tokoh yang anti-Belanda. Sikap anti yang sama, yang mengalir pada darah sebagian besar masyarakat Ende sebenarnya.
Hari-hari berikut, Riwu menjadi pesuruh yang sangat taat kepada Bung Karno, Ibu Inggit, dan keluarganya. Pengabdian Riwu begitu total, sehingga Bung Karno pun mempercayainya secara total. Kepercayaan itu ditunjukkan Bung Karno ketika peran Riwu tidak saja menjadi pembantu, tetapi sekaligus pengawal Bung Karno.
Benar. Tidak lama berselang, “Tidak sekali pun Bung Karno melangkah lebih dari dua meter tanpa pengawalan dari saya.” Begitu Riwu mengilustrasikan betapa ia mempertaruhkan hidupnya untuk berada di dekat Bung Karno, ke mana pun Bung Karno berurusan. Kisah itu berlanjut sampai ke pembuangan berikutnya di Bengkulu, bahkan sampai ke Jakarta hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945.
Benar. Tidak lama berselang, “Tidak sekali pun Bung Karno melangkah lebih dari dua meter tanpa pengawalan dari saya.” Begitu Riwu mengilustrasikan betapa ia mempertaruhkan hidupnya untuk berada di dekat Bung Karno, ke mana pun Bung Karno berurusan. Kisah itu berlanjut sampai ke pembuangan berikutnya di Bengkulu, bahkan sampai ke Jakarta hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945.
Tentang Bengkulu, ia mencatat banyak sekali peristiwa dramatik. Tentang proklamasi, ia pun memiliki kisah lain yang sungguh heroik. Riwu, selama 14 tahun menjadi orang dekat, dekat, sangat dekat dengan Bung Karno. (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Bung Karno Marah kepada Ibu Wardoyo



Sedikitnya ada dua kejadian yang menggambarkan kemarahan Bung Karno kepada kakak kandungnya, Sukarmini Wardoyo, atau sering dipanggil Ibu Wardoyo. Kemarahan yang pada waktu itu, cukup beralasan, sekaligus menggambarkan kepribadian Sukarno. Sekalipun begitu, kemarahan Bung Karno bersifat spontan, sesuai karakternya yang memang meledak-ledak, terlebih jika mendengar, melihat, dan merasakan sesuatu yang mengusik nuraninya.
Sekalipun begitu, harus dikemukakan terlebih dahulu di sini, bahwa pada galibnya, hubungan persaudaraan Bung Karno dan kakaknya, Ibu Wardoyo, sangatlah dekat. Bahkan, anak-anak Bung Karno juga sangat dekat dengan budenya. Tak heran, manakala Fatmawati meninggalkan Istana, frekuensi kunjungan Ibu Wardoyo ke Istana menjadi semakin intens. Sebaliknya, Guntur, Mega, Rachma, Sukma, dan Guruh senang jika kedatangan budenya.
Kiranya, gambaran di atas cukup bagi kita untuk meyakini, bahwa jalinan tali persaudaraan Bung Karno dengan kakaknya, sangatlah kuat. Itu artinya, sekali lagi harus dikemukakan di sini, jika Bung Karno sampai marah kepada “mbakyu”-nya, harus pula dipahami sebagai sebuah ekspresi kasih.
Baiklah. Kiranya cukup penggambaran mengenai hubungan Bung Karno dan Ibu Wardoyo. Menjawab pertanyaan, “Lantas, apa yang membuat Bung Karno marah kepada kakaknya?”
Kemarahan pertama ditunjukkan Bung Karno ketika ia mengetahui Ibu Wardoyo berlatih main tenis lapangan, dan kemudian menggemari tenis lapangan sebagai olahraga rutin. Permainan tenis lapangan, oleh Bung Karno disebut sebagai permainan mewah dan jauh dari suasana batin rakyat Indonesia. Maklumlah, pada waktu itu, sekitar tahun 50-an, olahraga tenis lapangan memang hanya dimainkan kalangan orang-orang kaya. Bung Karno tidak mau salah satu anggota keluarganya memainkan olahraga orang kaya itu.
Lantas, kemarahan apa lagi?

Kali ini, kemarahan besar. Lagi-lagi, Ibu Wardoyo-lah alamat amarah Bung Karno. Kemarahan itu dipicu dari upaya seorang pengusaha Belanda untuk memasukkan proposal proyek kepada pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, dalam rangka mengegolkan proposal tersebut, pengusaha Belanda itu melakukan pendekatan khusus kepada Ibu Wardoyo. Celakanya, Ibu Wardoyo menyanggupi permintaan pengusaha Belanda itu, membawa proposal tadi kepada Sukarno, adiknya. Kemudian, diserahkanlah proposal itu kepada ajudan, untuk diteruskan kepada Sukarno.
Satu hal, Ibu Wardoyo lupa, Sukarno dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia, adalah Presiden bagi bangsa dan negaranya, bukan presiden untuk saudaranya. Karenanya, ia sangat marah ketika menerima proposal itu dari ajudan, dan sang ajudan mengatakan bahwa proposal itu merupakan titipan Ibu Wardoyo, kakaknya. Dengan geram, Bung Karno meremas proposal itu dan membantingnya ke lantai.
Nah, bersambung ke penuturan ajudan Bung Karno, Bambang Widjanarko terkait peristiwa di atas. Penuturan tadi, sekaligus membenarkan bahwa peristiwa itu bukan isapan jempol. Bambang bercerita, bahwa suatu hari ia dipanggil Bung Karno masuk kamarnya di Istana Merdeka. “Bambang, saya tidak mau bertemu Mbakyu Wardoyo dalam satu bulan, saya sedang marah kepadanya. Lebih baik kamu usahakan agar Mbakyu tidak datang ke Istana ini.”
Bambang tahu, itu tugas berat dan rumit. Sebab di sisi lain, ia mengetahui betul kedekatan Bung Karno dengan Ibu Wardoyo, serta kedekatan Ibu Wardoyo dengan putra-putri Bung Karno. Tapi, toh Bambang harus menjawab, “Siap, Pak.”
Bambang yang tidak tahu duduk persoalan sebenarnya, segera menghubungi Pak Hardjowardoyo, Kepala Rumah Tangga Istana. Dari Pak Hardjo pula, Bambang mendapatkan cerita seperti terpapar di atas. Sedikit yang membedakan, versi Pak Hardjo adalah, bahwa Bung Karno tahu ada pengusaha Belanda “memakai” Ibu Wardoyo untuk mengegolkan proyek ke Presiden Sukarno, justru dari sebuah suratkabar Belanda.
Bambang yang tidak tahu duduk persoalan sebenarnya, segera menghubungi Pak Hardjowardoyo, Kepala Rumah Tangga Istana. Dari Pak Hardjo pula, Bambang mendapatkan cerita seperti terpapar di atas. Sedikit yang membedakan, versi Pak Hardjo adalah, bahwa Bung Karno tahu ada pengusaha Belanda “memakai” Ibu Wardoyo untuk mengegolkan proyek ke Presiden Sukarno, justru dari sebuah suratkabar Belanda.
Dalam banyak kesempatan, baik lisan maupun melalui sikap yang tegas, Bung Karno selalu menanamkan kepada istri-istri, anak-anak, dan keluarga, bahwa yang menjadi Presiden adalah Sukarno, sedangkan yang lain –istri, anak, saudara– adalah rakyat biasa. Para istri, anak-anak dan anggota keluarga, secara umum, menyadari dan memahami sepenuhnya. Karenanya, yang tampak pada diri Sukarno, baik semasa hidup maupun setelah jazadnya menyatu dengan bumi, adalah sosok seorang Presiden yang begitu kuat dan mandiri. (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Bung Karno Melamar Rahmi Tengah Malam





Di Palestina ada Yasser Arafat, di Indonesia ada Mohamad Hatta. Keduanya sama-sama ber-“Nazar” atau berikrar tidak akan menikah sebelum negaranya merdeka. Karenanya, Bung Karno, dalam suatu kesempatan yang rileks pasca kemerdekaan, menanyakan tentang calon pasangan hidup. Setidaknya karena dua alasan. Pertama, Indonesia sudah merdeka. Kedua, usia Hatta tidak muda lagi, 43 tahun.

Hatta tidak menampik topik melepas masa lajang. Terlebih, Bung Karno pun menyatakan siap menjadi mak comblang, bahkan melamarkan gadis yang ditaksirnya. Ketika Bung Karno bertanya kepada Hatta ihwal gadis mana yang memikat hatinya, Hatta menjawab, “Seorang gadis yang kita jumpai waktu kita berkunjung ke Institut Pasteur Bandung. Dia begini, begitu…. tapi saya belum tahu namanya.”
Usut punya usut, selidik punya selidik, gadis Parahyangan yang ditaksir Hatta adalah putri keluarga Rahim (Haji Abdul Rahim). Maka, ketika kira-kira sebulan setelah proklamasi Bung Karno berunjung ke Bandung, ia sempatkan mampir ke rumah keluarga Rahim di Burgermeester Koops Weg, atau yang sekarang dikenal sebagai Jl. Pajajaran No. 11. Bung Karno bertamu hampir tengah malam, jam23.00.

foto: Meutia Hatta dan Halida Hatta
Meski sempat diingatkan ihwal jam yang menunjuk tengah malam, tapi Bung Karno tetap keukeuh bertamu malam itu juga. Ia berdalih, tidak menjadi soal, karena ia kenal baik dengan keluarga Rahim. Persahabatan lama yang telah terjalin sejak Bung Karno kuliah di THS (sekarang ITB) Bandung. Apa lacur, setiba di rumah keluarga Rahim, ia disambut dampratan dari Ny. Rahim. Sebuah dampratan antarteman, mengingat Bung Karno datang bertamu tidak kenal waktu.
Untuk mereda dampratan tadi, dipeluklah Ny. Rahim dan diutarakanlah niatnya, “Saya datang untuk melamar.” Tuan dan Ny. Rahim bertanya serempak, “Melamar siapa? Untuk siapa?” Bung Karno langsung menjawab, “Melamar Rahmi untuk Hatta.” Dalam kisah lain diceritakan, adik Rahmi, yang bernama Titi, sempat mempengaruhi Rahmi supaya menolak lamaran Bung Karno, dengan alasan, Hatta jauh lebih tua dari Rahmi.

Berkat “rayuan” Bung Karno pula akhirnya Rahmi menerima pinangan tadi. Bung Karno meminta Rahmi melihat Fatmawati yang juga berbeda usia cukup jauh dengan Bung Karno, tetapi toh mereka bahagia. Alkisah, Hatta dan Rahmi resmi menikah di Megamendung pada tanggal 18 November 1945, hanya disaksikan keluarga besar Rahim, keluarga besar Bung Karno dan Fatmawati.
Dari pernikahan itu, lahirlah putri pertama mereka, Meutia Farida yang lahir di Yogyakarta 21 Maret1947. Nama Meutia datang dari neneknya yang asli Aceh. Sedangkan Farida diambil dari nama permaisuri Raja Farouk dari Mesir yang cantik jelita. Setelah itu, disusul kelahiran putri keduanya, Gemala, dan putri ketiga Halida Nuriah. (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Cicak dan Siul Perkutut di Penjara Banceuy



Masuk-keluar penjara bagi Sukarno adalah konsekuensi perjuangan. Penjara Banceuy adalah satu kisah tersendiri dalam perjalanan hidup pahlawan proklamator kita. Aktivitas politiknya bersama wadah PNI telah menyeretnya ke jerat hukum, hukum Hindia Belanda tentunya! Ia dituding –atau tepatnya diskenariokan– sebagai provokator yang sedia melakukan pemberontakan.
Dalih itu pula yang dijadikan pembenar bagi Belanda untuk menyergap, menggerebek, dan membekuk Sukarno dan kawan-kawan seperjuangan. Awal tahun 1930 ia diringkus dan dijebloskan ke Penjara Banceuy. Bangunan penjara yang didirikan abad ke-19 itu, kondisinya kotor, bobrok, dan tua. Di dalamnya terdapat dua bagian sel, masing-masing untuk tahanan politik, dan tahanan pepetek. Sebuah sebutan untuk rakyat jelata.
Sukarno sebagai tahanan politik, menempati Blok F kamar nomor 5. Teman seperjuangan, Gatot di sel 7, Maskun di sel nomor 9, dan Supriadinata 11. Lebar sel yang ditempati Sukarno hanyalah 1,5meter persegi, yang separuhnya sudah terpakai untuk tidur. Sel itu tak berjendela, pengap, berpintu besi, dengan lubang kecil yang hanya bisa dipakai mengintip lurus ke depan. Sukarno merasakan betapa lembab, pekat, dan melemaskan suasana “kuburan” Banceuy.
Teman Sukarno selama di Banceuy hanya cicak-cicak di dinding. Ketika makanan diantar, ia akan berbagi nasi dengan cicak-cicak itu. “Teman” yang lain? Adalah bayangan-bayangan ghaib yang hingga ajalnya, Sukarno sendiri tak pernah bisa memecahkannya.

Yang pertama adalah bayangan ketika ia merebahkan diri, memejamkan mata, dan tangan kanannya membesar… besar… besar… bahkan serasa lebih besar dari ruang sel itu sendiri. Kemudian secara perlayan berangsur mengecil hingga ke ukuran normal. Membesarnya tangan kanan, hanya bisa diduga sebagai satu perlambang akan besarnya kekuasaan yang ada pada tangan Sukarno di kelak kemudian hari. Entahlah.
Bayangan yang lain adalah suara burung perkutut. Ini tentu ganjil, mengingat penjara Banceuy terletak di pusat kota Bandung, tidak ada burung hidup di sekitar penjara. Namun ketika malam telah larut, suasana sunyi senyap, Sukarno mendengar suara burung perkutut, bersiul, menyanyi, begitu jelas hingga seolah ia rasakan ada di pangkuannya. Anehnya, tak seorang pun pernah mendengarnya, kecuali Sukarno.
Cicak-cicak di dinding serta suara burung perkutut di ujung malam, adalah sahabat Sukarno melewati hari-hari yang berat di Penjara Banceuy. (roso daras)
Cicak-cicak di dinding serta suara burung perkutut di ujung malam, adalah sahabat Sukarno melewati hari-hari yang berat di Penjara Banceuy. (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Gemblengan Sukamiskin




Dua tahun lamanya BK mendekam di Penjara Sukamiskin, meski persidangan tahun 1930 itu, majelis hakim mengganjarnya dengan hukuman 4 tahun penjara. Berkat pembelaannya yang dikenal sebagai “Indonesia Menggugat”, kasus yang menikam BK tersebar hingga ke Belanda. Banyak ahli hukum negeri Kincir Angin itu memprotes dan mengkritik hukuman atas BK, yang notabene tidak berdasar. Semua tuduhan tak pernah bisa dibuktikan dalam persidangan.
Atas berbagai protes itulah, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengubah masa hukuman BK menjadi dua tahun. Alhasil, 31 Desember 1931, ia dibebaskan. Sebelum ia menghirup udara bebas, telah tersebar sebuah tulisan dengan judul “Saya Memulai Kehidupan Baru”. Sipir penjara yang melepas BK hingga ke pintu gerbang Penjara Sukamiskin pun bertanya, “Ir. Sukarno, dapatkah tuan menerima kebenaran kata-kata ini? Apakah tuan betul-betul akan memulai kehidupan baru?” BK segera memegang tiang pintu kebebasan dengan tangan kanannya, dan menjawab, “Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekan, dan saya meninggalkan penjara dengan pikiran yang sama.”


Begitulah, seorang Sukarno memegang teguh prinsipnya, sekalipun selama dua tahun, ia telah melewati siksaan dahsyat, yang terutama adalah pengasingan dirinya di sebuah sel yang begitu lembab. Sampai-sampai, jika ia diberi waktu untuk keluar sel di siang hari, ia segera menuju pelataran dan berbaring telentang di atas tanah. Berjemur ala Sukarno. Menurutnya, itulah satu-satunya cara untuk mengeringkan tubuh dan tulang-tulangnya yang paling dalam, setelah sekian lama dibenamkan dalam sel yang dingin, pekat dan lembab.
Kisah heroik selama dalam penjara, terus terpupuk. Sandi-sandi komunikasi antara dirinya dengan elemen pejuang di luar penjara, senantiasa terjalin. Setiap butir telor yang dikirim istrinya, Inggit Garnasih, selalu diraba BK sebelum dikupas untuk dimakan. Jika ia mendapati satu lubang jarum, artinya keadaan lancar. Jika dua titik lubang jarum, artinya ada pejuang yang tertangkap. Jika tiga titik, artinya terjadi penyergapan besar-besaran.
Sandi juga dikirim lewat berbagai cara. Suatu ketika, Inggit mengirimkan kitab Alquran. BK segera mengingat tanggal Quran itu dikirim, kemudian membuka pada surah di halaman yang sesuai tanggal dikirimnya Alquran tadi. Nah, tangannya akan meraba di bagian bawah halaman yang dimaksud. Maka pada abjad yang dititik menggunakan jarum jahit, akan ia rangkai menjadi kata. Kata dirangkai menjadi kalimat, sehingga tersusunlah informasi. Begitulah sekelumit kisah Sukarno di balik penjara Sukamiskin. (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Amerika, “Go To Hell With Your Aid”


Puncak kekesalan Bung Karno kepada Amerika Serikat, diteriakkan dalam kalimat yang sangat terkenal hingga hari ini, “Amerika… go to hell with your aid“. Kalimat yang diucapkan dengan menggelegar karena meregang amarah, tentu saja mengagetkan banyak pihak. Bukan saja karena Amerika adalah negeri super power dan Indonesia adalah negeri yang baru merdeka, lebih dari itu, pada hakikatnya, sebagai negara baru, Indonesia sejatinya masih membutuhkan bantuan negara lain.
Karenanya, dalam biografi yang dituturkan melalui Cindy Adams, ia memerlukan sedikitnya empat paragraf untuk menjelaskan sikap kerasnya kepada Amerika Serikat. Pertama-tama ia jelaskan arti kata “bantuan”. Ia ingatkan sekali lagi, yang dimaksud bantuan adalah bukan cuma-cuma, bukan hadiah dari seorang paman yang kaya raya kepada keponakanya yang melarat. “Bantuan” itu adalah suatu pinjaman dan harus dibayar kembali.
Sementara Amerika mengira seolah-olah Indonesia adalah ibarat orang melarat, kemudian mereka berkata, “Ambillah… ambillah saudara kami yang malang dan melarat… ambillah uang ini.” Sungguh suatu anggapan yang tidak betul. “Anggapan yang munafik!” pekik Bung Karno. Bantuan mereka, pada hakikatnya adalah utang yang harus dibayar kembali berikut segala bunganya.
Amerika menaruh perhatian kepada negara terbelakang seperti Indonesia ketika itu, karena dua alasan. Pertama, karena Indonesia merupakan pasar yang baik untuk barang-barang mereka. Kedua, mereka takut Indonesia menjadi komunis.
Manakala negara yang dibantu tidak “berkelakuan baik” sesuai kehendak mereka, dengan semena-mena lantas mengancam, “Kami tidak akan berikan lagi, kecuali jika engkau berkelakuan baik!” Tentang ini, sikap Presiden Filipina Manuel Quezon sama dengan Bung Karno. Quezon pernah mengatakan, “Lebih baik pergi ke neraka tanpa Amerika, daripada pergi ke surga bersama-sama dengan dia.”
Bung Karno menegaskan, Amerika Serikat tidak memberikan hadiah cuma-cuma kepada Indonesia. Sementara, Indonesia yang ingin berdiri di atas kaki sendiri, sejatinya tidak menginginkan bantuan cuma-cuma. Bahkan, Indonesia sangat berterima kasih atas semua bantuan yang telah Amerika ulurkan kepada bangsa Indonesia. “Kami sama sekali tidak meminta Amerika supaya memberi uang secara cuma-cuma. Kami sudah mengemis-ngemis selama hidup, dan kami takkan melakukannya lagi. Ada pertolongan lain yang dapat mereka berikan, yakni persahabatan.”
Dan, manakala para senator berpidato di muka umum tentang pencabutan bantuan kepada Indonesia. Pemerintah Amerika mengumumkan di koran-koran di seluruh dunia tentang pencabutan bantuan kepada Indonesia… ketika itu pula Bung Karno merasa Amerika Serikat bukanlah sahabat. Mereka tidak saja menampar muka Sukarno di muka umum, tetapi juga merendahkan Indonesia sebagai bangsa.
Karenanya, Bung Karno menyesalkan, “(Jika ingin mencabut bantuan) Mengapa tidak mencabutnya diam-diam? Mengapa harus berteriak-teriak mengumumkan kepada dunia? Janganlah perlakukan Sukarno di muka umum, seperti seorang anak yang tak berguna dengan menolak memberinya gula-gula lagi, sampai dia menjadi anak yang manis. Oleh karena sikap yang begitu itu, maka Sukarno tidak punya pilihan lain kecuali mengatakan, ‘Persetan dengan bantuanmu!’” (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Kruschev Meledek Pesawat Bung Karno


Tahun 60-an, saat usia kemerdekaan kita masih berbilang belasan tahun, Indonesia –dan Bung Karno– sudah menjadi bangsa dan negara yang dihargai oleh para pemimpin negara besar, utamanya penguasa Blok Kapitalis (Amerika Serikat) dan Blok Komunis (Rusia atau Uni Sovyet). Kedua negara adidaya yang terlibat perang dingin karena beda ideologi tadi, saling berebut pengaruh terhadap Indonesia.
Sikap Bung Karno? Sangat jelas, dia menyuarakan kepada dunia sebagai negara nonblok. Sekalipun begitu. bukan berarti Indonesia adalah negara yang istilah Bung Karno hanya “duduk thenguk-thenguk” tanpa berbuat apa-apa bagi peradaban dunia. Nonblok yang aktif. Karena itu pula, Bung Karno berhasil menggalang kekuatan-kekuatan baru yang ia wadahi dalam NEFO (New Emerging Forces), sebuah kekuatan baru, terdiri atas negara-negara yang baru merdeka, atau sedang berkembang.
Nah, ini cerita tentang pesawat terbang. Dalam berbagai lawatan ke luar negeri, pemerintah Indonesia menyewa pesawat komersil Pan America (PanAm), lengkap beserta kru untuk rombongan Presiden Sukarno. Ini sempat jadi masalah diplomatik, ketika Bung Karno hendak berkunjung ke Rusia, memenuhi undangan Kamerad Nikita Kruschev. Sebab waktu itu, tidak ada satu pun perusahaan penerbangan Amerika Serikat yang mempunyai hubungan tetap dengan Moskow.
Rusia terang-terangan keberatan bila Bung Karno datang menggunakan PanAm dan mendarat di Moskow. Karena itu, pihak pemerintah Rusia mengajukan usul, akan menjemput Bung Karno di Jakarta menggunakan pesawat Rusia yang lebih besar, lebih perkasa, Ilyushin L.111.
Sudah watak Bung Karno untuk tidak mau didikte oleh pemimpin negara mana pun. Termasuk dalam urusan pesawat jenis apa yang hendak ia gunakan. Karenanya, atas usulan Rusia tadi, Bung Karno menolak. Bahkan jika kedatangannya menggunakan PanAm ditolak, ia dengan senang hati akan membatalkan kunjungan ke Rusia.
Pemerintah Rusia pun mengalah. Ya… mengalah kepada Sukarno, presiden dari sebuah negara yang belum lama berstatus sebagai negara merdeka, lepas dari pendudukan Belanda dan Jepang.
Akan tetapi, tampaknya Rusia tidak mau kehilangan muka sama sekali, dengan mendaratnya sebuah pesawat Amerika –musuhnya– di tanah Moskow. Alhasil, ketika pesawat PanAm jenis DC-8mendarat di bandar udara Moskow, petugas traffic bandara langsung mengarahkan pesawat yang ditumpangi Sukarno dan rombongan parkir tepat di antara dua pesawat terbang “raksasa” buatan Rusia, jenis Ilyushin seri L.111. Seketika, tampak benar betapa kecilnya pesawat Amerika itu bila dibanding dengan pesawat jet raksasa buatan Rusia.
Belum cukup dengan aksi “unjuk gigi” tadi, Kruschev yang menjemput Bung Karno di lapangan terbang, masih pula menambahkan, “Hai, Bung Karno! Itukah pesawat kapitalis yang engkau senangi? Lihatlah, tidakkah pesawat-pesawatku lebih perkasa?”
Mendengar ucapan itu, Bung Karno hanya tersenyum lebar dan menjawab, “Kamerad Kruschev, memang benar pesawatmu kelihatan jauh lebih besar dan gagah, tetapi saya merasa lebih comfortable dalam pesawat PanAm yang lebih kecil itu.” (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
“Cinta Lodeh” Bung Karno dan Hartini


Hartini, adalah seorang janda beranak lima, ketika “ditemukan” Bung Karno di Salatiga, tahun 1952. Kisah asmara Bung Karno dan Hartini, patut diangkat, demi memperingati hari pernikahan mereka 55tahun yang lalu, tepatnya 7 Juli 1954 di Bogor.
Sungguh kisah yang unik dan dramatik. Hari itu, Bung Karno dijadwalkan melakukan kunjungan ke Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Presiden dijadwalkan singgah di Salatiga. Demi mendengar Bung Karno akan singgah, sejak pagi rakyat kota Salatiga dan sekitarnya berbondong-bondong menjejali Lapangan Tamansari. Di lapangan itulah Bung Karno akan menyapa rakyat Salatiga dalam pidato yang selalu ditunggu-tunggu rakyat dengan antusias.
Ibarat cerita layar perak, setting berganti ke suasana kesibukan luar biasa di kediaman Walikota Salatiga. Ya, karena di kediaman Walikota itulah Bung Karno akan rehat sejenak sekaligus makan siang. Sepasukan ibu-ibu sibuk menyiapkan ini dan itu, mulai dari menyiapkan meja jamuan makan sampai ke urusan masak-memasak di dapur.
Di antara kaum perempuan yang sedang sibuk di dapur, tampak sosok perempuan berwajah lembut, berkulit bersih kuning langsat, perawakan semampai, rambut hitam sepinggang, dan… senyum manis tersungging di bibir yang merekah indah. Dialah Siti Suhartini, yang tinggal sekitar 100 meter dari rumah Walikota Salatiga, dan kebetulan pula, pagi tadi ia “dijawil” Walikota untuk ikut membantu di dapur, menyambut kedatangan Presiden Sukarno. Wanita yang di kemudian hari dikenal sebagai Hartini itu, memasak sayur lodeh untuk melengkapi masakan-masakan yang lain. Ia sendiri merasa “pe-de” dengan masakah sayur lodehnya.
Sejenak, kita pindah setting ke Lapangan Tamansari. Bung Karno sudah tiba, dan rakyat mengelu-elukan dengan semarak. Sejurus kemudian, lautan manusia diam seketika diam, suasana hening, tersirep oleh suasana magis, menanti Bung Karno mengucap kata. Rakyat siap *****ik “Merdeka!!!” sekuat-kuatnya jika nanti Bung Karno menguluk salam. Ternyata, Bung Karno membuka pidato dengan lantunan tembang “Suwe Ora Jamu”….
Suwe ora jamu
Jamu pisan jamu kapulogo
Suwe ora ketemu
Ketemu pisan nang Solotigo…
Kontan saja, rakyat bergemuruh, ada yang bertepuk tangan, ada yang ikut menyanyi, ada yang *****ik Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!! Jelaslah… hati rakyat benar-benar terjerat oleh daya pikat Bung Karno. Begitu yang tampak pada suasana selanjutnya, ketika Bung Karno berpidato dengan berapi-api, dan rakyat khidmat menyimak kata demi kata, menikmat alunan tinggi dan rendah suara Singa Podium.
Jamu pisan jamu kapulogo
Suwe ora ketemu
Ketemu pisan nang Solotigo…
Kontan saja, rakyat bergemuruh, ada yang bertepuk tangan, ada yang ikut menyanyi, ada yang *****ik Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!! Jelaslah… hati rakyat benar-benar terjerat oleh daya pikat Bung Karno. Begitu yang tampak pada suasana selanjutnya, ketika Bung Karno berpidato dengan berapi-api, dan rakyat khidmat menyimak kata demi kata, menikmat alunan tinggi dan rendah suara Singa Podium.
Singkat kalimat, usai berpidato Bung Karno diiringkan pejabat daerah, ajudan dan pengawal, menuju kediaman Walikota Salatiga. Sesampai di sana, hidangan telah lengkap tersaji. Aroma masakan olahan dapur dari para juru masak pilihan, menyambar-nyambar hidung siapa saja di dekatnya. Sang perut pun mengirim sinyal “lapar” kepada tuannya. Jadilah Bung Karno dan yang lain, segera menikmati hidangan makan siang.
Bung Karno? Dia langsung menyambar sayur lodeh di depannya. Ya… sayur lodeh masakan Hartini di dapur tadi. Lahap. Lahap sekali, karena sayur lodeh memang merupakan menu kesukaan Bung Karno. Begitu enaknya sayur lodeh di rumah Walikota Salatiga, sampai-sampai seusai jamuan, Bung Karno menyempatkan diri bertanya, “Siapa yang masak sayur lodeh yang enak ini. Saya ingin mengucap terima kasih kepadanya.”
Anda bayangkan sendirilah suasana ketika itu. Di mana ada Bung Karno, di situ ada antusiasme siapa pun untuk mendekat, melihat, bahkan kalau boleh mendekap, bahkan mencium kakinya jika diizinkan. Artinya, ketika Bung Karno menanyakan si pemasak lodeh, para perempuan yang bertugas di dapur menjadi gaduh. Maka, Sri Hartini pun didorong-dorong oleh teman-temannya untuk maju… maju… menunjukkan diri, menemui Presiden, dan menerima ucapan terima kasihnya.
Dalam buku Srihana-Srihani Biografi Hartini Sukarno, terpapar pengakuan Hartini ihwal momen yang kemudian mengubah jalan hidupnya, di rumah Walikota Salatiga. Ia mengaku, gugup dan senang ketika maju dan mengulurkan tangan kepada Bung Karno. Hartini ingat betul, Bung Karno menjabat tangan Hartini begitu hangat dan… lama! Bung Karno benar-benar terkesiap oleh kecantikan Hartini dengan segala kelebihannya sebagai sesosok perempuan. Sambil tetap memegang tangan Hartini, Bung Karno bertanya basi, “Rumahnya di mana? Anaknya berapa? Suami?”
Demi waktu, hari itu Sukarno jatuh cinta kepada Hartini pada pandangan pertama. Itu pula yang dikatakan Sukarno di kemudian hari dalam surat-surat cintanya kepada Hartini. (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
“Tuhan Telah Mempertemukan Kita, Tien…”

“Ketika aku melihatmu untuk kali yang pertama, hatiku bergetar. Mungkin kau pun mempunyai perasaan yang sama. Ttd: …. SRIHANA. Begitu salah satu surat cinta yang datang kemudian. Ihwal nama SRIHANA? Itu adalah nama samaran Bung Karno. Adalah Bung Karno yang juga memberikan nama SRIHANI kepada Hartini, sebagai nama samaran pula. Alhasil, surat-menyurat Bung Karno – Hartini selanjutnya terus mengalir menggunakan nama samaran SRIHANA – SRIHANI.

Inilah babak berikut, pasca pertemuan pandang yang pertama antara Presiden Sukarno dan Hartini di rumah Walikota Salatiga. Perjalanan dinas selanjutnya, menyisakan satu ruang yang hampa di ruang hatinya. Acara-acara kepresidenan selanjutnya, menyisakan satu ruang kosong di ruang pikirnya. Benar, sebongkah rasa, sebutir pikir, telah tertinggal di Salatiga, bersama kenangan mendebarkan saat jumpa Hartini, jagoan pemasak sayur lodeh.
Bahkan, sesampai di Jakarta, bayang-bayang wajah ayu Hartini tetap meliuk-liuk indah menemani tatapan-tatapan kosong Sukarno. Senyum manis dari bibir yang indah, serta sorot mata lembut tapi menusuk, menjadi santapan lamunan Sukarno.
Bangkit dari himpitan cinta, bangkit dari lamunan, Sukarno langsung mengambil secarik kertas, memungut sebuah pena, dan menulis sebaris kata. Untaian kata-kata cinta tadi, tercatat dalam sejarah cinta Sukarno – Hartini, sebagai surat cinta pertama.
Bangkit dari himpitan cinta, bangkit dari lamunan, Sukarno langsung mengambil secarik kertas, memungut sebuah pena, dan menulis sebaris kata. Untaian kata-kata cinta tadi, tercatat dalam sejarah cinta Sukarno – Hartini, sebagai surat cinta pertama.
“Tuhan telah mempertemukan kita Tien, dan aku mencintaimu. Ini adalah takdir.” Itulah goresan kata, yang kemudian dititipkan pada seseorang untuk segera disampaikan kepada Hartini nun di Salatiga sana. Si penerima surat yang dipanggil dengan panggilan kesayangan “Tien”, kaget bukan kepalang. Belum selesai hatinya galau demi menerima surat cinta dari Presiden Republik Indonesia, sudah datang lagi telegram-telegram, dan surat-surat bernada cinta selanjutnya.
“Ketika aku melihatmu untuk kali yang pertama, hatiku bergetar. Mungkin kau pun mempunyai perasaan yang sama. Ttd: …. SRIHANA. Begitu salah satu surat cinta yang datang kemudian. Ihwal nama SRIHANA? Itu adalah nama samaran Bung Karno. Adalah Bung Karno yang juga memberikan nama SRIHANI kepada Hartini, sebagai nama samaran pula. Alhasil, surat-menyurat Bung Karno – Hartini selanjutnya terus mengalir menggunakan nama samaran SRIHANA – SRIHANI.
Tahun 1953, tercatat sebagai pertemuan kedua antara Bung Karno dan Hartini. Lokasinya? Di Candi Prambanan. Selama itu pula, Bung Karno terus menebar jala cinta, melalui ungkapan kata-kata puitis dalam surat-suratnya. Hartini? Ia makin gundah… makin gulana….
Bahkan, ketika Bung Karno melamarnya untuk bersedia dijadikan istri kedua, Hartini tidak serta merta memberi jawab. Bung Karno mengulang lamarannya, Hartini masih tetap belum bersedia. Lagi, Bung Karno melamar lagi, Hartini belum juga memutus kata.
Janda dalam usia 28 tahun, dengan paras yang begitu ayu mempesona, sangat mungkin masih mendamba kehadiran seorang pria. Akan tetapi, Hartini tidak pernah menduga, jika pria yang dimaksud adalah seorang Presiden. Hartini tidak pernah menyangka bahwa pria yang dimaksud telah memiliki first lady, Fatmawati.
Dalam kecamuk pikir dan gemuruh hati, Hartini hanya bisa berpaling kepada kedua orangtuanya, Pak Osan Murawi dan Mbok Mairah. Orangtua Hartini menjawab pertimbangan putrinya dengan mengatakan, “Dimadu itu abot (berat), biarpun oleh raja atau presiden. Opo kowe kuat? Tanyakan hatimu. Apa pun keputusanmu kami memberi restu.”
Satu tahun berhubungan cinta melalui surat dan sedikit pertemuan, akhirnya Hartini tak kuasa menolak pinangan Bung Karno, dengan segala konsekuensi yang telah dipikirkannya. Apalagi, benih-benih cinta yang disemai Bung Karno, memang telah tumbuh subuh di hati Hartini. Hartini begitu mengagumi Bung Karno, terlebih setelah bertubi-tubi menerima kiriman surat cinta, dalam bahasa yang begitu indah, serta diselang-seling sisipan mutiara kata dalam bahasa Belanda dan Inggris.
Jawaban Hartini, “Ya… dalem bersedia menjadi istri Nandalem” (Ya, saya bersedia menjadi istri tuan), tapi dengan syarat, Ibu Fat tetap first lady, saya istri kedua. Saya tidak mau Ibu Fat diceraikan, karena kami sama-sama wanita.” (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Misteri Tongkat Komando Bung Karno


Dalam banyak dokumentasi foto Bung Karno, tidak sedikit yang menampakkan sosok Putra Sang Fajar itu memegang atau mengempit tongkat komando. Dalam hierarki kemiliteran, posisinya sebagai Panglima Tertinggi, tentu saja merupakan hal yang wajar jika ia sering terlihat memegang tokat komando. Sama seperti yang sering kita lihat, ketika Panglima TNI, Panglima Kodam, Kapolri, memegang tongkat komando.
Akan tetapi, tidak begitu dari kacamata spiritual. Kalangan yang percaya hal-hal ghaib. Kalangan yang percaya adanya kekuatan tertentu pada benda-benda keramat. Kalangan yang percaya adanya hal-hal metafisik yang tidak bisa dibahas dengan kalimat lugas, dan tidak bisa dinalar dengan pola pikir normal. Nah, kelompok ini, begitu eksis di Indonesia, sejak dulu sampai sekarang.
Di antara kalangan mereka, percaya betul bahwa tongkat komando Bung Karno bukanlah sembarang tongkat. Tongkat komando Bung Karno adalah tongkat sakti, yang berisi keris pusaka ampuh. Bahkan, kayu yang dibuat sebagai tongkat pun bukan sembarang kayu, melainkan kayu pucang kalak. Pucang adalah jenis kayu, sedangkan Kalak adalah nama tempat di selatan Ponorogo, atau utara Pacitan. Di pegunungan Kalak terdapat tempat persemayaman keramat. Nah, di atas persemayaman itulah tumbuh pohon pucang.
Ada begitu banyak jenis kayu pucang, tetapi dipercaya pucang kalak memiliki ciri khas. Salah satu cara untuk mengetes keaslian kayu pucang kalak, pegang tongkat tadi di atas permukaan air. Jika bayangan di dalam air menyerupai seekor ular yang sedang berenang, maka berarti kayu pucang kalak itu asli. Tetapi jika yang tampak dalam bayangan air adalah bentuk kayu, itu artinya bukan pucang kalak. Pucang biasa, yang banyak tumbuh di seantero negeri.
Begitulah sudut pandang mistis masyarakat spiritual terhadap tongkat komando Bung Karno. Alhasil, tidak sedikit yang menghubungkan dengan besarnya pengaruh Sukarno. Tidak sedikit yang menghubungkan dengan kemampuannya menyirap kawan maupun lawan. Tidak sedikit yang menghubungkan dengan “kesaktian” Sukarno, sehingga lolos dari beberapa kali usaha pembunuhan.
Apa kata Bung Karno? “Ah… itu semua karena lindungan Allah, karena Ia setuju dengan apa-apa yang aku kerjakan selama ini. Namun kalau pada waktu-waktu yang akan datang Tuhan tidak setuju dengan apa-apa yang aku kerjakan, niscaya dalam peristiwa (pembunuhan) itu, aku bisa mampus.” (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Bung Karno, Dikutuk seperti Bandit, Dipuja Laksana Dewa


Begitulah Sukarno. Sepertinya, tidak ada manusia di abad ke-20 yang menimbulkan begitu banyak perasaan pro dan kontra seperti dia. Kepada penulis biografinya, Cindy Adams, Bung Karno mengibaratkan dirinya dikutuk seperti bandit, dan dipuja laksana Dewa.
Dubes senior Inggris di tahun 60-an pernah berkirim surat ke alamat Downing Street 10 London (alamat Kantor Perdana Menteri). Tulisnya, “Presiden Sukarno tidak dapat dikendalikan, tidak dapat diramalkan dan tidak dapat dikuasai. Dia seperti tikus yang terdesak.”
Media massa Barat membuat laporan-laporan yang mendiskreditkan Sukarno, meski sumbernya seorang abang becak, yang entah faktual entah fiktif. Hal itu tentu menjadi kontradiktif dengan sisi yang lain, yang menggambarkan begitu ia dipuja bagaikan Dewa.
Tak jarang, seorang kakek-kakek datang ke Istana, memaksa bertemu Presidennya sebelum ajal menjemput. Ada pula kisah seorang nelayan uzur, berjalan kaki 23 hari lamanya, untuk dapat bersujud mencium kaki Sukarno. Ia menyatakan, dirinya sudah berjanji, sebelum mati akan melihat wajah presidennya dan menunjukkan kecintaan serta kesetiaan kepadanya. Termasuk foto ilustrasi di atas, seorang lelaki berjalan kaki dari kampungnya, membawa seikat talas untuk dipersembahkan kepada presidennya. Ketika berjumpa, ia pun langsung bersimpuh, bersujud dan mencium kaki Sukarno.
Tidak sedikit kisah-kisah unik lain. Seperti yang dilakukan seorang petani kelapa yang sedang bersedih karena sudah berbulan-bulan anaknya sakit keras. Suatu malam ia bermimpi, bahwa ia harus pergi menemui Bung Karno untuk meminta air bagi kesembuhan anaknya. Bung Karno sendiri memenuhi permintaan rakyat yang dicintainya. Diambilkannya air ledeng biasa dan diserahkannya kepada petani kelapa tadi.
Dalam persoalan di atas, Bung Karno sama sekali tidak bisa bersoal-jawab dengan mereka. Apalagi, Sukarno paham betul, sebagian masyarakat kita, utamanya orang Jawa, banyak yang percaya kepada ilmu kebatinan. Termasuk petani kelapa yang bersikeras meminta air kepada Bung Karno. Seminggu kemudian, ia mendengar anak petani kelapa tadi telah sembuh.
Tidak jarang, ketika Bung Karno hadir dalam suatu acara, muncul pula cerita-cerita unik. Ia ingat ketika menghadiri suatu acara di pedalaman Jawa Tengah. Seorang perempuan desa mendatangi pelayan Bung Karno dan membisikkan, “Jangan biarkan orang mengambil piring Presiden. Berikanlah kepada saya sisanya. Saya sedang mengandung dan saya ingin anak laki-laki. Saya mengidamkan seorang anak seperti Bapak. Jadi tolonglah, biarlah saya memakan apa-apa yang telah dijamah sendiri oleh Presidenku,” ujar perempuan itu bersemangat.
Di Pulau Bali, masyarakat percaya bahwa Sukarno adalah penjelmaan Dewa Wishnu, Dewa Hujan dalam agama Hindu. Karenanya, di musim kemarau pun, ketika Sukarno datang ke Bali, senantiasa dimaknai sebagai turunnya hujan. Mereka yakin, kedatangannya membawa restu. Bahkan pernah terjadi, ketika Bung Karno terbang ke Bali dalam musim kering, tepat setelah Bung Karno tiba, hujan turun bagaikan dicurahkan dari langit. (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
“Tuan Punya Bom Atom, tapi Saya Punya Seni”



Adalah kebiasaan Presiden AS, John F. Kennedy menerima tamu-tamu negara di lantai atas Gedung Putih. Tapi protokol itu tidak berlaku bagi Sukarno, Presiden Republik Indonesia. Dan itu dinyatakan langsung kepada protokol Gedung Putih, “Kennedy mesti turun. Sambut saya di bawah. Kalau tidak, saya tidak akan datang.”
Entah bagaimana si petugas protokol itu menyampaikannya ke Kennedy. Tetapi yang jelas, ketika Bung Karno datang ke Gedung Putih, Kennedy turun ke ke lantai bawah, dan menyambutnya dengan ramah. Setelah ritual pertemuan dua kepala negara sekadarnya, barulah keduanya bersama-sama menaiki tangga ke atas, diiringi para staf kedua petinggi negara tadi.
Bukan hanya itu. Bung Karno bahkan diberi kesempatan berpidato di Gabungan Kongres dan Senat Amerika Serikat. Ini sangat jarang terjadi, Kepala Negara disambut di Amerika Serikat dengan Sidang Gabungan Kongres dan Senat.

O, ya… mundur sedikit ke belakang, ke saat di mana Bung Karno tiba di Gedung Putih, disambut Kennedy di bawah. Ketika itu, Kennedy sempat memperkenalkan para staf yang mendampinginya. Salah satunya adalah Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Charles Wilson, nama lengkapnya Charless Nesbitt Wilson. Politisi kelahiran Texas tahun 1 Juni 1933, alias satu zodiak dengan Bung Karno.
Ketika diperkenalkan, Wilson yang berperawakan gagah dan berwajah macho, maju hendak menyalami Presiden Sukarno. Saat itulah muncul spontanitas humor diplomasi yang sungguh luar biasa dari seorang Sukarno, presiden negara berkembang yang belum lama lepas dari penjajahan Belanda.
Kepada Wilson, Bung Karno tidak sekadar mengulurkan tangan untuk bersalaman. Lebih dari itu, Bung Karno dalam bahasa Inggris yang fasih berkata, “Kombinasi baju dan dasi Tuan tidak bagus,” berkata begitu sambil Bung Karno membetulkan ikatan dasi yang kelihatan miring. Selesai merapikan dasi Menhan Amerika Serikat, Bung Karno melanjutkan ucapannya, “Tuan boleh punya bom atom, tapi kami punya seni yang tinggi.”
Bayangkan, mental siapa yang tidak koyak. Apalagi Bung Karno melakukan semua gerakan dan ucapan tadi dengan sangat penuh percaya diri, disaksikan begitu banyak orang. Dari hal-hal kecil seperti itulah, dignity, harga diri kita sebagai bangsa dibangun oleh Bung Karno, sehingga Indonesia tidak dipandang sebelah mata. (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Burung Elang Terbang Sendirian



Terlalu banyak kisah heroik menjelang dan pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jalannya revolusi, penuh riak gelombang. Panas-dingin suhu politik. Naik-turun irama pergerakan. Jalinan hubungan antara sang pemimpin dengan yang dipimpin, tak urung mengalami pasang dan surut.
Bung Karno tak pernah sepi dari kontroversi. Lihat sejarah Romusha. Tengok sejarah pembentukan PETA. Tidak semua langkah Sukarno didukung semua elemen perjuangan. Beberapa pemuda bahkan menentang keras, mengecam, bahkan mengutuk Sukarno yang mereka tuding sebagai “kolaborator”. Benar. Sikap Sukarno yang mau bekerja sama dengan Jepang untuk beberapa hal, dinilai keblinger, dan melenceng dari cita-cita menuju Indonesia merdeka.
Persoalannya, seperti yang Bung Karno keluhkan kepada Cindy Adams, penulis biografinya, bahwa ia tidak mungkin keliling Indonesia, mendatangi satu per satu orang dan menjelaskan semua langkah dan keputusannya. Termasuk yang cap terhadapnya sebagai kolabortor Jepang. Bung Karno hanya punya keyakinan. Bung Karno hanya punya perhitungan. Bung Karno hanya punya ego yang sangat kuat.
Alhasil, ketika tahun 1943 Jepang mendirikan PETA, Bung Karno sendiri yang memilihkan pemuda-pemuda cakap untuk menjadi anggotanya, satu di antaranya Gatot Mangkupraja, pemberontak PNI yang senasib dengan Bung Karno ketika dijebloskan ke penjara Sukamiskin tahn 1929. Sikap Bung Karno didasari perhitungan, dengan menjadi anggota PETA, maka para prajurit muda asli putra bangsa, akan mendapat pelajaran-pelajaran penting tentang dasar-dasar kemiliteran, ilmu berperang, strategi bertempur, dan penguasaan peralatan perang modern.

Sementara, sekelompok muda yang progresif menentang bergabung dengan PETA, bahkan mengutuk Sukarno yang mendukung PETA, demi membantu Jepang melawan Sekutu. Itu pula yang diucapkan seorang dokter muda yang merawat Bung Karno di rumah sakit, sekitar tahun 1943. Katanya, “Banyak orang mengatakan, dengan memasuki tentara (PETA) yang didirikan oleh Jepang hanya berarti kita akan membantu Jepang saja.”
Bung Karno marah dan menukas, “Itulah pandangan yang dangkal. Orang yang berpikir demikian, tidak bisa melihat jangka yang lebih jauh ke depan. Tujuan yang pokok adalah melengkapi alat perjuangan bagi kemerdekaan. Tidak ada maksud lain daripada itu.”
Dokter itu membantah, “Tapi ingatlah bahwa Jepang datang kemari untuk menjajah. Dia itu musuh. Bertempur di samping mereka berarti membantu Fasisme!”
Bung Karno menjawab, “Kukatakan, pendirian yang demikian itu terlalu picik. Tapi, baiklah, Jepang itu datang kemari untuk menjajah dan harus diterjang keluar. Akan tetapi ingat, bahwa mereka adalah penjajah yang bisa diperalat. Saya membantu pembentukan PETA — ya! Tapi bukan untuk mereka! Tidakkah dokter memahaminya? Untuk kita! Untuk engkau! Untukku! Untuk Tanah Air kita! Atau, apakah dokter tetap mau menjadi orang jajahan sampai hari kiamat?
Bung Karno menjawab, “Kukatakan, pendirian yang demikian itu terlalu picik. Tapi, baiklah, Jepang itu datang kemari untuk menjajah dan harus diterjang keluar. Akan tetapi ingat, bahwa mereka adalah penjajah yang bisa diperalat. Saya membantu pembentukan PETA — ya! Tapi bukan untuk mereka! Tidakkah dokter memahaminya? Untuk kita! Untuk engkau! Untukku! Untuk Tanah Air kita! Atau, apakah dokter tetap mau menjadi orang jajahan sampai hari kiamat?
Dokter itu belum puas, dan terus berbantah dengan Sukarno, “Rakyat menyatakan tentang Bung Karno, bahwa……..”
“Rakyat tidak mengatakan apa-apa!” Bung Karno memotong kalimat dokter. “Jikalau mereka yakin, bahwa saya tidak menempuh jalan yang paling baik, tentu rakyat tidak akan mengikuti saya, bukan? Coba, apakah memang rakyat tidak mengikuti saya?”
“Tidak.”
“Bukankah mereka mengikuti saya?”
“Ya, seratus persen.”
“Jadi, rakyat tidak mengatakan apa-apa. Hanya beberapa pemuda yang kepala panas saja yang mengatakan….”
“Bahwa Bung Karno bekerja sama dengan musuh,” dokter melengkapi kalimat Bung Karno.
Tapi toh, dialog itu tidak bisa meredam para pemuda yang disebut Bung Karno kepala panas. Makanya, Bung Karno pada waktu-waktu itu, masih sering menjumpai secarik kertas berisi surat kaleng yang diselipkan di bawah pintu. Salah satu dari surat itu menyebutkan, “Karena kami dipimpin oleh seseorang yang bersemangat tikus, kami tidak berani berjuang. Akan tetapi jika kami dipimpin oleh seseorang yang bersemangat banteng, kami akan bertempur mati-matian.”
Atas kejadian itu, Bung Karno hanya bergumam, “Ah… ini hari yang jelek.” Hati Sukarno benar-benar sedih. Dalam keadaan tertekan seperti itu, satu kalimat yang bisa membuatnya tenang kembali, “Bebek berjalan berbondong-bondong, akan tetapi burung elang terbang sendirian.” (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Hari-hari Terakhir Bung Karno (1)






Bung Karno, di akhir hayatnya sangat nista. Ia dinista oleh penguasa ketika itu. Ia sakit, dan tidak mendapat perawatan yang semestinya bagi seorang Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus tokoh pemersatu bangsa. Bahkan untuk sekadar bisa menghirup udara Jakarta (dari pengasingannya di Bogor), ia harus menulis surat dengan sangat memelas kepada Soeharto.
Mengenang hari-hari terakhir Bung Karno, saya sengaja menukil kisah sedih yang dipaparkan Reni Nuryanti dalam bukunya Tragedi Sukarno, Dari Kudeta Sampai Kematiannya. Harapannya, kita semua bisa berkaca dari sejarah. Detail kisah mengharu biru, dari praktik-praktik biadab aparat militer ketika itu kepada Bung Karno selama hidup dalam “kerangkeng” Orde Baru di Wisma Yaso, cepat atau lambat akan terbabar.
Hari-hari terakhir Bung Karno ini, saya penggal mulai dari peristiwa tanggal 16 Juni 1970 ketika Bung Karno dibawa ke RSPAD (Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto). Ia dibawa pukul 20.15, harinya Selasa. Ada banyak versi mengenai peristiwa ini. Di antaranya ada yang menyebutkan, Sukarno dibawa paksa dengan tandu ke rumah sakit.

Hal itu ditegaskan oleh Dewi Sukarno yang mengkonfirmasi alasan militer, bahwa Bung Karno dibawa ke RS karena koma. Dewi mendapat keterangan yang bertolak belakang. Waktu itu, tentara datang membawa tandu dan memaksa Bung Karno masuk tandu. Tentara tidak menghiraukan penolakan Bung Karno, dan tetap memaksanya masuk tandu dengan sangat kasar. Sama kasarnya ketika tentara mendorong masuk tubuh Bung Karno yang sakit-sakitan ke dalam mobil berpengawal, usai menghadiri pernikahan Guntur. Bahkan ketika tangannya hendak melambai ke khalayak, tentara menariknya dengan kasar.
Adalah Rachmawati, salah satu putri Bung Karno yang paling intens mendampingi bapaknya di saat-saat akhir. Demi mendengar bapaknya dibawa ke RSPAD, ia pun bergegas ke rumah sakit. Betapa murka hati Rachma melihat tentara berjaga-jaga sangat ketat. Hati Rachma mengumpat, dalam kondisi ayahandanya yang begitu parah, toh masih dijaga ketat seperti pelarian. “Apakah bapak begitu berbahaya, sehingga harus terus-menerus dijaga?” demikian hatinya berontak.
Dalam suasana tegang, tampak Bung Karno tergolek lemah di sebuah ruang ujung becat kelabu. Tak ada keterangan ruang ICU atau darurat sebagaimana mestinya perlakuan terhadap pasien yang koma. Tampak jarum infus menempel di tangannya, serta kedok asam untuk membantu pernapasannya.
Untuk menggambarkan kondisi Sukarno ketika itu, simak kutipan saksi mata Imam Brotoseno, “Lelaki yang pernah amat jantan dan berwibawa –dan sebab itu banyak digila-gilai perempuan seantero jagad, sekarang tak ubahnya bagai sesosok mayat hidup. Tiada lagi wajah gantengnya. Kini wajah yang dihiasi gigi gingsulnya telah membengkak, tanda bahwa racun telah menyebar kemana-mana. Bukan hanya bengkak, tapi bolong-bolong bagaikan permukaan bulan. Mulutnya yang dahulu mampu menyihir jutaan massa dengan pidato-pidatonya yang sangat memukau, kini hanya terkatup rapat dan kering. Sebentar-sebentar bibirnya gemetar menahan sakit. Kedua tangannya yang dahulu sanggup meninju langit dan mencakar udara, kini tergolek lemas. (roso daras)
Hari-hari Terakhir Bung Karno (2)

Hari kedua, 17 Juni 1970, Sukarno tampak lebih baik dari hari sebelumnya. Tapi, ia tidak mau makan. Bahkan, obat-obatan yang diberikan dokter pun enggan meminumnya. Setiap kali dokter hendak memberi suntikan pun, Bung Karno selalu menolak. Rachmawati menerka, Bung Karno mengetahui bahwa semua pengobatan selama ini hanya untuk memperlemah dirinya. Dalam kacamata politik, pengobatan dengan misi pembunuhan.
Karenanya, kondisi Sukarno makin lemah dari hari ke hari. Hingga saat itu Rachma berani bertanya kepada tim dokter yang merawat, dalam hal ini ia bertanya kepada Ketua Tim Dokter yang merawat Bung Karno, yakni Prof Mahar Mardjono, “Mengapa sakit komplikasi yang diderita bapak dibiarkan begitu saja. Mengapa tidak dilakukan cuci darah?” Mahar hanya menjawab sambil lalu, sehingga Rachma berkesimpulan, dokter-dokter itu tidak benar-benar merawat Sang Proklamator Bangsa. Bahkan, para dokter tampak tak punya rasa iba sedikit pun.
Lebih sakit hati Rachma ketika dr Mahar mengatakan, “Alat itu sedang dipesan dari Inggris, dan belum tentu ada. Kalaupun ada, kapan datangnya, tidak tahu.” Keterangan Mahar ini, di kemudian hari dibenarkan anggota dokter lain, “Sebenarnya sudah lama, tim dokter telah mengusulkan agar alat itu dibeli. Tapi alat itu tak kunjung datang meski pembeliannya kabarnya telah dijajaki di Singapura dan Inggris.” Dan akhirnya, anggota tim dokter itu menambahkan, “jangan-jangan memang sengaja tidak dibeli….”
Dalam keterangan lain, situasi saat itu memang membuat tim dokter yang dipimpin Mahar Mardjono tak berdaya. Ada kekuatan besar yang bisa mengancam nyawa mereka seandainya mereka bekerja di luar kendali penguasa. Karenanya dalam suatu kesaksian terungkap, saat kondisi Bung Karno kritis, Prof dr Mahar Mardjono sempat menuliskan resep khusus, namun obat yang diresepkannya itu disimpan saja di laci oleh dokter yang berpangkat tinggi. Mahar mengemukakan hal itu kepada rekannya, dr Kartono Mohammad.

Kesaksian datang dari saksi lain yang juga mantan pejabat di era Sukarno. Menurutnya, adalah fakta bahwa Sukarno ditelantarkan oleh Soeharto pada waktu sakit. Saksi yang juga seorang purnawirawan tinggi militer itu juga mengungkapkan, perlakuan yang seragam terhadap Sukarno berasal dari sebuah instruksi, “Yang memberi instruksi adalah Soeharto,” katanya. (roso daras)
Hari-hari Terakhir Bung Karno (3)

Semua detik yang berdetak, semua menit yang lewat, semua jam yang bergulir, semua angin yang berembus… adalah duka sepanjang hari. Satu hari bernama tanggal 18, mungkin hanya bermakna 24 jam. Satu hari berikutnya yang bernama tanggal 19 Juni 1970, adalah bilangan 1440 menit, 86.400detik. Tapi semua itu adalah tusukan duri bagi Sukarno yang tengah tergolek lemah.
Sedangkan tanggal 20 Juni, tercatat sebagai simbol dwitunggal yang terpatri abadi. Sejarahlah yang berkuasa pada hari itu. Bung Hatta, datang menjenguk sahabat seperjuangan. Sementara, Bung Karno, seperti diberi kekuatan untuk menyaksikan kedatangan Sang Hatta. Maka, terjadilah pertemuan yang mengharu-biru, seperti dikisahkan Meutia Hatta dalam bukunya: Bung Hatta: Pribadinya dalam Kenangan.
Berkata lirih Sukarno kepada Hatta, “Hatta… kau di sini….?
Seperti diiris-iris hati Hatta melihat sahabatnya tergolek tanpa daya. Demi memompa semangat kepada sahabat, wajah teduh Bung Hatta menampakkan raut yang direkayasa, “Ya… bagaimana keadaanmu, No?” begitu Hatta membalas sapaan lemah Karno, dengan panggilan akrab yang ia ucapkan di awal-awal perjuangan. Hatta memegang lembut tangan Bung Karno. Bung Karno melanjutkan sapaan lemahnya, “Hoe at het met jou…” (Bagaimana keadaanmu?)
Seperti diiris-iris hati Hatta melihat sahabatnya tergolek tanpa daya. Demi memompa semangat kepada sahabat, wajah teduh Bung Hatta menampakkan raut yang direkayasa, “Ya… bagaimana keadaanmu, No?” begitu Hatta membalas sapaan lemah Karno, dengan panggilan akrab yang ia ucapkan di awal-awal perjuangan. Hatta memegang lembut tangan Bung Karno. Bung Karno melanjutkan sapaan lemahnya, “Hoe at het met jou…” (Bagaimana keadaanmu?)
Hatta benar-benar tak kuasa lagi merekayasa raut teduh. Hatta benar-benar tak kuasa menahan derasnya arus kesedihan demi mendengar sahabatnya menyapanya dalam bahasa Belanda, yang mengingatkannya pada masa-masa penuh nostalgi. Apalagi, usai berkata-kata lemah, Sukarno menangis terisak-isak. Lelaki perkasa itu menangis di depan kawan seperjuangannya. Seketika, Hatta pun tak kuasa membendung air mata. Kedua sahabat yang lama berpisah, saling berpegang tangan seolah takut terpisah. Keduanya bertangis-tangisan.
“No….”
Hanya kata itu yang sanggup Hatta ucapkan, sebelum akhirnya meledak tangis yang sungguh memilukan. Bibirnya bergetar menahan kesedihan, sekaligus kekecewaan. Bahunya terguncang-guncang karena ledakan emosi yang menyesakkan dada, yang mengalirkan air mata. Keduanya tetap berpegangan tangan. Bahkan, sejurus kemudian Bung Karno minta dipasangkan kacamata, agar dapat melihat sahabatnya lebih jelas.
Selanjutnya, Bung Karno hanya diam. Mata keduanya bertatapan… mereka berbicara melalui bahasa mata. Sungguh, ada sejuta makna yang tertumpah pada sore hari yang bersejarah itu. Selanjutnya, Bung Karno hanya diam. Diam, seolah pasrah menunggu datangnya malaikat penjemput, guna mengantarnya ke swarga loka, terbang bersama cita-cita yang kandas di tangan bangsanya sendiri. (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Hari-hari Terakhir Bung Karno (4)



Siapa yang tak murka, demi mengetahui bahwa selama kurang lebih 1,5 tahun “dikerangkeng” di Wisma Yaso, Bung Karno, mantan Presiden Republik Indonesia, tokoh pemersatu dan proklamator bangsa, ternyata hanya diserahkan perawatannya secara penuh kepada dr Soeroyo. Siapakah dokter Soeroyo? Dia bukanlah dokter spesialis, melainkan dokter hewan!
Ia masuk-keluar Wisma Yaso dengan perawat-perawat yang tidak jelas didatangkan dari mana. Bahkan obat-obatan yang dicekokkan ke Bung Karno pun sama sekali tidak tepat. Ia hanya memberinya duvadilin (mencegah kontraksi ginjal), metadone (penghilang rasa sakit), royal jeli, suntikan vitamin B1 dan B12, serta testoteron. Selain itu, Sukarno tiap malam juga minum valium.
Tiap malam minum valium selama tahunan, tentu saja membuat tidurnya tak lagi terkontrol. Akibatnya Sukarno mulai sering merasakan pusing. Setiap itu pula, perawat memberinya obat pengurang rasa sakit, novalgin.
Perawatan yang sembrono juga sering terjadi, ketika Bung Karno terbangun tengah malam dan muntah darah, dokter Soeroyo hanya memberinya vitamin. Sementara, dokter Mahar Mardjono yang disebut-sebut sebagai ketua tim, sama sekali tidak pernah hadir ke Wisma Yaso. Itu semua terungkap dalam dokumen yang lebih 27 tahun tersimpan oleh Siti Khadijah, yang tak lain adalah istri dokter Soeroyo. Benar adanya, bahwa sejarah pada akhirnya akan mengalir menemukan jalan kebenarannya sendiri. Benar pula, bahwa ada kecenderungan yang seolah tersusun rapi, tentang “pembunuhan” terhadap Sukarno.
Tidak banyak cerita, tanggal 21 Juni 1970, pukul 07.00 WIB, Bung Karno menghembuskan nafas terakhirnya. Adalah dr Mahar Mardjono, satu-satunya orang yang menyaksikan “kepergian” Putra Sang Fajar. Keterangan yang ia kemukakan, “Pada hari Minggu, 21 Juni 1970, pukul 04.00 pagi, Bung Karno dalam keadaan koma. Saya dan dokter Sukaman terus berada di sampingnya. Menjelang pukul 07.00 pagi, dr Sukaman sebentar meninggalkan ruangan rawat. Saya sendiri berada di ruang rawat bersama Bung Karno. Bung Karno berbaring setengah duduk, tiba-tiba beliau membuka mata sedikit, memegang tangan saya, dan sesaat kemudian Bung Karno menghembuskan nafas yang terakhir.”
Tak lama berselang, keluarlah komunike medis:
1. Pada hari Sabtu tangal 20 Juni 1970 jam 20.30 keadaan kesehatan Ir. Sukarno semakin memburuk dan kesadaran berangsur-angsur menurun.
2. Tanggal 21 Juni 1970 jam 03.50 pagi, Ir Sukarno dalam keadaan tidak sadar dan kemudian pada jam 07.00 Ir Sukarno meninggal dunia.
3. Team dokter secara terus-menerus berusaha mengatasi keadaan kritis Ir Sukarno hingga saat meninggalnya.
1. Pada hari Sabtu tangal 20 Juni 1970 jam 20.30 keadaan kesehatan Ir. Sukarno semakin memburuk dan kesadaran berangsur-angsur menurun.
2. Tanggal 21 Juni 1970 jam 03.50 pagi, Ir Sukarno dalam keadaan tidak sadar dan kemudian pada jam 07.00 Ir Sukarno meninggal dunia.
3. Team dokter secara terus-menerus berusaha mengatasi keadaan kritis Ir Sukarno hingga saat meninggalnya.
Komunike itu ditandatangai Ketua Prof Dr Mahar Mardjono, dan Wakil Ketua Meyjan Dr (TNI-AD) Rubiono Kertopati.
Sementara itu, Syamsu Hadi suami dari Ratna Juami, anak angkat Bung Karno dan Inggit Ganarsih yang melihat jenazah Bung Karno melukiskan dengan baik, “Wajah almarhum begitu tenang. Seperti orang tidur saja nampaknya. Mata tertutup baik. Alis tebal tidak berubah, sama seperti dulu.” (roso daras)

___________________________________________________________________________________________________________________________
Ekspresi Duka Inggit, Fatma, Hartini, dan Dewi





Masih seputar suasana kelabu di hari-hari wafatnya Sukarno, Sang Proklamator. Ini tentang bagaimana para istri dan mantan istri presiden yang gallant itu bereaksi, bersikap, dan bertutur ihwal kepergian lelaki yang begitu dipuja. Ternyata, sekalipun memiliki perasaan yang sama dalam hal cinta, tetapi berbeda-beda ekspresi mereka menerima kematian mantan suami atau suami mereka.
Inggit Garnasih, istri kedua Sukarno yang dinikahi tahun 1923, adalah wanita yang dengan setia mengikuti dan mendukung perjuangan Sukarno sejak usia 21 tahun. Ia bahkan turut serta dalam setiap pengasingan Bung Karno, mulai dari Ende sampai Bengkulu. Ia lahir tahun 1888, lebih tua 12tahun dari Bung Karno. Itu artinya, saat “nKus” panggilan kesayangan Inggit kepada Bung Karno, wafat, usia Inggit 82 tahun.
Nah, di usia yang sepuh, dan dalam kondisi sakit… ia menerima berita duka pada hari Minggu, 21 Juni 1970. Ia tergopoh-gopoh berangkat dari Bandung menuju Jakarta, ditemani putri angkatnya, Ratna Juami. Dalam batin, ia harus memberi penghormatan kepada mantan suami yang telah ia antar ke pintu gerbang kemerdekaan.
Setiba di Wisma Yaso, di tengah lautan massa yang berjubel, berbaris, antre hendak memberi penghormatan terakhir, Inggit –tentu saja– mendapat keistimewaan untuk segera diantar mendekat ke peti jenazah. Di dekat tubuh tak bernyawa di hadapannya, Inggit berucap, “Ngkus, geuning Ngkus tehmiheulan, ku Inggit di doakeun…” (Ngkus, kiranya Ngkus mendahului, Inggit doakan….). Sampai di situ, suaranya terputus, kerongkongan terasa tersumbat. Badannya yang sudah renta dan lemah, terhuyung diguncang perasaan sedih. Sontak, Ibu Wardoyo, kakak kandung Bung Karno (nama aslinya Sukarmini) memapah tubuh tua Inggit.

Lain lagi Fatmawati, istri ketiga Bung Karno yang pergi meninggalkan Istana setelah Bung Karno menikahi Hartini. Ia adalah sosok perempuan yang teguh pendirian. Ia sudah bertekad tidak akan datang ke Wisma Yaso. Karenanya, begitu mengetahui ayah dari lima putra-putrinya telah meninggal, ia segera memohon kepada Presiden Soeharto agar jenazah suaminya disemayamkan di rumahnya di Jl. Sriwijaya, Kebayoran Baru, meski sebentar. Sayang, Soeharto menolak permintaan Fatmawati.
Hati Fatma benar-benar galau. Antara jerit hati ingin melihat wajah suami untuk terakhir kali, dengan keteguhan prinsip. Bahkan, putra-putrinya pun tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusan Fatma untuk tetap tinggal di rumah. Meski, atas kesepakatan semua pihak, peti jenazah tidak ditutup hingga batas akhir jam 24.00, dengan harapan, Fatma datang pada detik-detik terakhir. Apa hendak dikata, Fatma tak juga tampak muka.
Pengganti kehadiran Fatma, adalah sebuah karangan bunga dari si empunya nama. Dengan kalimat pendek dan puitis, Fatma menuliskan pesan, “Tjintamu yang menjiwai hati rakyat, tjinta Fat”… Sungguh mendebarkan kalimat itu, bagi siapa pun yang membacanya.

Bagaimana pula dengan Hartini? Ah… melihat Hartini, hanya duka dan duka sepanjang hari. Wajah cantik keibuan, mengguratkan kelembutan. Sinar matanya penuh kasih sayang… Ia tak henti menangis. Hartini, salah satu istri yang begitu dicintai Sukarno, sehingga dalam testamennya, Sukarno menghendaki agar jika mati, Hartini dimakamkan di dekat makamnya. Ia ingin selalu dekat Hartini, wanita lembut keibuan yang dinikahinya Januari 1952.
Kebetulan, Hartini pula yang paling intens merawat dan menemani Bung Karno hingga akhir hayatnya. Sampai-sampai, Rachmawati, salah satu putri Bung Karno yang kebetulan juga paling intens menemani bapaknya di hari-hari akhir kehidupannya, memuji Hartini sebagai istri yang sangat setia dan baik hati. Rachma yang semula berperasaan tidak menyukai Hartini –dan ini wajar saja– menjadi dekat dan akrab dengan Hartini.
Semula, Rachma hanya berpura-pura baik dengan Hartini di depan bapaknya. Sebab, Rachma tahu betul, bapaknya begitu senang jika ada Hartini di dekatnya. Bapaknya begitu mencintai Hartini. Dan… dengan kesabaran, ketelatenan, dan perhatian tulus Hartini kepada Bung Karno di hari-hari akhir hidupnya, sontak membuka mata hati Rachma tentang sosok Hartini. Sejak itulah tumbuh keakraban dan kecintaan Rachma kepada Ibu Hartini.

Lain Inggit, beda Fatma, dan tak sama pula sikap Hartini… adalah ekspresi imported wife, si jelita Ratna Sari Dewi, wanita Jepang benama asli Naoko Nemoto. Wanita kelahiran tahun 1940 yang dinikahi Bung Karno 3 Maret 1962 itu memang dikenal lugas. Ia datang ke Jakarta bersama Kartika Sari (4 th) pada tanggal 20 Juni 1970 pukul 20.20 malam. Mengetahui suaminya lunglai tak berdaya, dirawat dalam penjagaan ketat tak manusiawi.
Hati Dewi teriris, terlebih bila mengingat anaknya sama sekali belum pernah berjumpa dengan ayahnya. Dalam catatan, Dewi pernah berkunjung ke Wisma Yaso saat hamil, tapi tentara melarangnya masuk. Dewi marah, karena kesulitan yang dialaminya. Ia, sebagai istri sah Sukarno, tidak bisa leluasa menengok apalagi menemani hari-hari Sukarno yang sedang bergulat dengan maut.
Latar belakang budaya yang berbeda, membuat Dewi kelihatan sangat vokal pada zamannya. Ia pernah marah besar kepada Soeharto dengan melontarkan ucapan pedas melalui surat terbuka tanggal 16 April 1970.
Begini sebagian isi surat itu:
“Tuan Soeharto, Bung Karno itu saya tahu benar-benar sangat mencintai Indonesi dan rakyatnya. Sebagai bukti bahwa meskipun ada lawannya yang berkali-kali menteror beliau, beliau pun masih mau meberikan pengampunan kalau yang bersangkutan itu mau mengakui kesalahannya. Dibanding dengan Bung Karno, maka ternyata di balik senyuman Tuan itu, Tuan mempunyai hati yang kejam. Tuan telah membiarkan rakyat, yaitu orang-orang PKI dibantai. Kalau saya boleh bertanya, ‘Apakah Tuan tidak mampu dan tidak mungkin mencegahnya dan melindungi mereka agar tidak terjadi pertumpahan darah?”
“Tuan Soeharto, Bung Karno itu saya tahu benar-benar sangat mencintai Indonesi dan rakyatnya. Sebagai bukti bahwa meskipun ada lawannya yang berkali-kali menteror beliau, beliau pun masih mau meberikan pengampunan kalau yang bersangkutan itu mau mengakui kesalahannya. Dibanding dengan Bung Karno, maka ternyata di balik senyuman Tuan itu, Tuan mempunyai hati yang kejam. Tuan telah membiarkan rakyat, yaitu orang-orang PKI dibantai. Kalau saya boleh bertanya, ‘Apakah Tuan tidak mampu dan tidak mungkin mencegahnya dan melindungi mereka agar tidak terjadi pertumpahan darah?”
Bukan hanya itu. Penampilan Dewi yang masih tampak begitu cantik di suasana duka, seperti menjadi icon. Terlebih dengan keterbukaan sikapnya. Seperti saat dengan penuh emosi ia melabrak Harjatie, istri Bung Karno yang telah diceraikan itu, sebagai seorang istri yang menyia-nyiakan Bung Karno, menuduh Harjatie meninggalkan Sukarno di masa-masa sulit. Harjatie pun menangis, dan bergerak meninggalkan tempat itu.
Begitulah, empat dari (setidaknya) delapan wanita yang pernah diperistri Bung Karno. Sama dalam mencinta, beda dalam mengekspresikan duka. (roso daras)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Soeharto Datang, Setelah Bung Karno “Terbang”
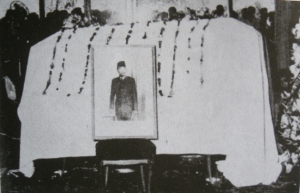





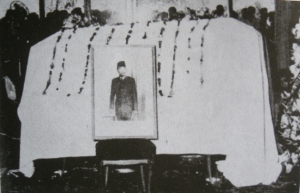
Akses informasi yang terbatas, penjagaan yang sangat ketat, mengakibatkan tidak satu pun wartawan dapat mengikuti hari-hari terakhir Bung Karno, baik ketika masih dalam perawatan, maupun ketika Bung Karno mangkat. Satu-satunya informasi yang secara terbuka didapat wartawan ketika itu adalah pengumuman resmi tim dokter ihwal meninggalnya Ir. Sukarno, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, pagi hari 21 Juni 1970 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Sejurus kemudian, jenazah Bung Karno dibawa ke Wisma Yaso, rumah Dewi Sukarno (sekarang Museum Satria Mandala). Wisma yang tak berpenghuni beberapa hari terakhir, sangat menyedihkan keadaannya. Sementara itu, masyarakat ibukota yang sudah mendengar berita kematian Bung Karno, berjejal merangsek ke arah Wisma Yaso, hendak memberi penghormatan terakhir kepada tokoh yang dikagumi dan dicintai.
Sejurus kemudian, jenazah Bung Karno dibawa ke Wisma Yaso, rumah Dewi Sukarno (sekarang Museum Satria Mandala). Wisma yang tak berpenghuni beberapa hari terakhir, sangat menyedihkan keadaannya. Sementara itu, masyarakat ibukota yang sudah mendengar berita kematian Bung Karno, berjejal merangsek ke arah Wisma Yaso, hendak memberi penghormatan terakhir kepada tokoh yang dikagumi dan dicintai.

Tak luput, Presiden Soeharto dan Ibu Tien juga hadir di sana. Sebelumnya, pukul 07.30, atau 30menit setelah berpulangnya Bung Karno ke Rahmatullah, Soeharto dan Ibu Tien datang ke RSPAD. Dalam otobiografinya, Soeharto mengatakan, “Waktu saya mendengar beliau meninggal pada tanggal21 Juni 1970, cepat saya menjenguknya di rumah sakit. Setelah itu barulah aku berpikir mengenai pemakamannya”. Dan hari itu, menjadi pertemuan terakhir setelah Soeharto menjatuhkan Bung Karno, dan tidak menemuinya lagi sejak 1967.

Sebelumnya, Soeharto hanya menyadap berita kematian Sukarno dari para petugas. Dalam beberapa kesempatan, sikap Soeharto terhadap Sukarno dikatakannya sebagai “mikul dhuwur, mendem jero”. Falsafah Jawa itu sejatinya mulia, karena mengandung makna menghormati setinggi-tingginya, dan menyimpan atau mengubur aib sedalam-dalamnya. Falsafah itu oleh Soeharto diartikan dengan mengasingkan Sukarno, dan “membunuhnya” pelan-pelan dalam kerangkengan kejam di Wisma Yaso hingga menjelang ajal.
Tanggal 22 Juni, atau sehari setelah kematiannya, jenazah Sukarno dibawa ke Blitar, Jawa Timur lewat Malang. Sholat jenazah sudah dilakukan malamnya, dengan imam Menteri Agama KH Achmad Dahlan, sedang sholat jenazah oleh rakyat, diimami Buya Hamka.
Tanggal 22 Juni, atau sehari setelah kematiannya, jenazah Sukarno dibawa ke Blitar, Jawa Timur lewat Malang. Sholat jenazah sudah dilakukan malamnya, dengan imam Menteri Agama KH Achmad Dahlan, sedang sholat jenazah oleh rakyat, diimami Buya Hamka.

Masih menurut buku TRAGEDI SUKARNO tulisan Reni Nuryanti, ada catatan menarik lain tentang makam Sukarno, yang ternyata hanya dimakamkan di bekas Taman Makam Pahlawan Bahagia Sentul. Nah, ihwal dimakamkannya jenazah Sukarno di Blitar, Soeharto berdalih, adanya dua kehendak, antara permintaan almarhum Bung Karno agar dimakamkan di Bogor, dan keinginan keluarga yang berbeda-beda. Karena itulah akhirnya diputuskan dimakamkan di Blitar.
Banyak pihak menduga, keputusan Soeharto itu sarat politik. Ia tidak menghiraukan testamen atau permintaan ahli kubur bernama Ir. Sukarno, Presiden RI pertama yang menghendaki jika meninggal, minta dimakamkan di Bogor. Para pihak menduga, ada kepentingan jangka panjang dari Soeharto untuk “mengubur lebih dalam” Sukarno beserta nama besar dan kecintaan rakyat kepadanya. Inilah yang di kemudian hari disebut sebagai “desukarnoisasi”, upaya menghapus nama Sukarno dari memori rakyat Indonesia.
Sebaliknya, jika jazad Bung Karno dimakamkan di Bogor, sama saja menghambat langkah Soeharto untuk menenggelamkan nama besar Sukarno. Jarak Bogor – Jakarta terlalu dekat, sehingga kenangan rakyat tetap melekat. Ini yang secara politis akan mengganggu kewibawaannya. Langkah dan kebijakan untuk melarang semua ajaran Sukarno, langkah menjebloskan 0rang-orang dekat Sukarno ke dalam tahanan tanpa pengadilan, adalah bentuk lain dari upaya Soeharto benar-benar menghabisi Sukarno.
Satu hal yang Soeharto lupa, bahwa kebenaran senantiasa akan mengalir menemukan jalannya sendiri. Sekalipun kebenaran itu sudah dibelokkan. Sekalipun kebenaran itu sudah disumbat. Sekalipun kebenaran itu sudah dikubur dalam-dalam. Dan… kebenaran niscaya akan mengalir dalam sungainya sejarah. (roso daras)
Banyak pihak menduga, keputusan Soeharto itu sarat politik. Ia tidak menghiraukan testamen atau permintaan ahli kubur bernama Ir. Sukarno, Presiden RI pertama yang menghendaki jika meninggal, minta dimakamkan di Bogor. Para pihak menduga, ada kepentingan jangka panjang dari Soeharto untuk “mengubur lebih dalam” Sukarno beserta nama besar dan kecintaan rakyat kepadanya. Inilah yang di kemudian hari disebut sebagai “desukarnoisasi”, upaya menghapus nama Sukarno dari memori rakyat Indonesia.
Sebaliknya, jika jazad Bung Karno dimakamkan di Bogor, sama saja menghambat langkah Soeharto untuk menenggelamkan nama besar Sukarno. Jarak Bogor – Jakarta terlalu dekat, sehingga kenangan rakyat tetap melekat. Ini yang secara politis akan mengganggu kewibawaannya. Langkah dan kebijakan untuk melarang semua ajaran Sukarno, langkah menjebloskan 0rang-orang dekat Sukarno ke dalam tahanan tanpa pengadilan, adalah bentuk lain dari upaya Soeharto benar-benar menghabisi Sukarno.
Satu hal yang Soeharto lupa, bahwa kebenaran senantiasa akan mengalir menemukan jalannya sendiri. Sekalipun kebenaran itu sudah dibelokkan. Sekalipun kebenaran itu sudah disumbat. Sekalipun kebenaran itu sudah dikubur dalam-dalam. Dan… kebenaran niscaya akan mengalir dalam sungainya sejarah. (roso daras)

Ratna Sari Dewi menatap jenazah suaminya. Tampak di belakang, Rachmawati, Megawati, Sukmawati.

Rakyat berjejal memberi penghormatan terakhir kepada Bung Karno. Sementara, sepasukan tentara berjaga-jaga dengan ketat dan senapan di tangan.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Pemakaman Bung Karno



Rakyat Indonesia dari penjuru Tanah Air, berjubel, tidak saja di sekitar Wisma Yaso tempat jenazah Bung Karno disemayamkan, tetapi juga di Blitar, Jawa Timur, tempat jazad Bung Karno dikebumikan. Seperti pengalaman pribadi mantan ajudan Bung Karno, Bambang Widjanarko. Ia merasa bagai tersambar petis demi mendengar kematian tokoh bangsa yang delapan tahun ia layani. Bambang yang ketika Bung Karno wafat sudah menjabat sebagai Asisten Kepala Personil Urusan Militer Mabes TNI-AL itu, bergegas menuju Wisma Yaso.
Wisma Yaso yang sejak siang sudah dijejali kerumunan rakyat yang hendak melayat, tidak juga surut hingga malam hari. Bambang pun masuk dalam antrian pelayat, yang berjalan menuju ruang tengah Wisma Yaso setapak demi setapak. Suasana ketika itu dilukiskan sebagai sangat mengharukan. Tidak terdengar percakapan, kecuali isak tangis, dan bisik-bisik pelayat. Di sudut ruang, masih tampak kerabat dan pelayat yang tak kuasa menahan jeritan hati yang mendesak di rongga dada, hingga tampak tersedu-sedu.
Tiba di dekat peti jenazah, Bambang melantunkan doa, “Ya Tuhan, Engkau telah berkenan memanggil kembali putraMu, Bung Karno. Terimalah kiranya arwah beliau di sisiMu. Sudilah Engkau mengampuni segala dosa-dosanya dan berkenanlah Engkau menerima segala tekad dan perbuatannya yang baik. Engkau Mahatahu ya Tuhan, dan Engkaulah Mahakuasa, aku mohon kabulkanlah doaku ini. Amin”
Segera setelah usai berdoa, Bambang menuju kamar lain, tempat keluarga BK berkumpul. Di sana tampak Hartini, Dewi, Guntur, Mega, Rachma, Sukma, Guruh, Bayu, dan Taufan. Mereka pun saling berangkulan. Sejurus kemudian, Sekmil Presiden, Tjokropranolo mendekati Bambang dan berkata, “Mas Bambang, kami mohon sedapatnya bantulah kami dalam menjaga dan melayani keluarga BK yang saat ini amat sedih dan emosional.” Bambang segera menukas, “Baik, tapi toong sampaikan hal ini kepada KSAL.”
Begitulah. Bambang sejak itu tak pernah jauh dari keluarga Bung Karno. Baginya, inilah bhakti terakhir yang dapat ia persembahkan bagi Bung Karno. Bambang juga berada di mobil bersama keluarga Bung Karno dalam perjalanan dari Wisma Yaso ke Halim, dari Halim terbang ke Malang, dan dari Malang jalan darat dua jam ke Blitar. Di situ, ia melihat rakyat berjejal di pinggir jalan, menangis menjerit-jerit, atau diam terpaku dengan air mata bercucuran.
Bambang yang duduk dekat Rachma tak kuasa menahan haru demi melihat begitu besar kecintaan rakyat kepada Bung Karno. Ia pun berkata pelan kepada Rachma, “Lihatlah, Rachma, rakyat masih mencintai Bung Karno. Mereka juga merasa kehilangan. Jasa bapak bagi nusa dan bangsa ini tidak akan terlupakan selamanya.” Rachma mengangguk.
Pemandangan yang sama tampak di Blitar hingga ke areal pemakaman. Ratusan ribu rakyat sudah menunggu. Bahkan militer harus ekstra ketat menjaga lautan manusia yang ingin merangsek mendekat, melihat, menyentuh peti jenazah Bung Karno.
Sementara itu, upacara pemakaman dengan cepat dilaksanakan. Panglima TNI Jenderal M. Panggabean menjadi inspektur upacara mewakili Pemerintah Republik Indonesia. Prosesi pemakaman berlanjut. Peti jenazah pelan-pelan diturunkan ke liang kubur. Tak lama kemudian, liang kubur mulai ditutup timbunan tanah… saat itulah meledak tangis putra-putri Bung Karno, yang kemudian sisusul ledakan tangis pelayat yang lain di sekitar makam. Bambang Widjanarko merasa hancur hatinya demi melihat penderitaan anak-anak Bung Karno ditinggal pergi bapaknya untuk selama-lamanya. Tanpa terasa, air mata Bambang mengalir lagi di pipi.
Akhirnya, selesailah upacara pemakaman Bung Karno yang berlangsung sederhana tetapi khidmat. Acara pun ditutup tanpa menunggu selesainya peletakkan karangan bunga. Meski rombongan resmi sudah meninggalkan makam, tetapi ribuan manusia tak beranjak. Bahkan aliran peziarah dari berbagai penjuru negeri, terus mengalir hingga malam. Mereka maju berkelompok-kelompok, meletakkan karangan bunga atau menaburkan bunga lepas di tangannya, kemudian berjongkok, atau duduk memanjatkan doa, menangis di dekat pusara Bung Karno.

Malam makin gelap, tetapi sama sekali tak menyurutkan lautan manusia mengalir menuju makam Bung Karno. Makin malam, makin gelap, tampak makin khusuk mereka bedoa. Ratusan orang meletakkan karangan bunga, ratusan orang menabur bunga lepas, tetapi puluhan ribu pelayat pergi membawa segenggam bunga. Alhasil, karangan bunga dan taburan bunga yang menggunung si sore hari, telah habis diambil peziarah lain selagi matahari belum lagi merekah di ufuk timur. Habis bunga, peziarah berikutnya menjumput segenggam tanah di pusara Bung Karno, dan dimasukkan saku celana. Tak ayal, tanah menggunduk di atas jazad Bung Karno pun menjadi rata. Inilah dalam ritual Jawa yang disebut “ngalap berkah”.
Seorang pelayat, dan ia adalah rakyat biasa, berkata, “Bung Karno adalah seorang pemimpin besar, Pak. Kami rakyat, sangat mencintainya. Sebagai kenangan saya bawa pulang sedikit bunga ini.”
Begitulah, karangan bunga, taburan bunga, bahkan gundukan tanah pun dijumput para peziarah. Yang tampak keesokan harinya, 23 Juni 1970 adalah pusara berhias tanah merah. Merah menyalakan semangat tiada padam. Biarpun jazad terkubur dalam tanah, semangat tak akan lekang dimakan waktu. Biar jazad hancur menyatu dengan tanah, tapi kobaran semangat perjuangan tetap menyala. Sukarno hanya mati jazad, namun ruh dan jiwanya tetap menyatu dengan rakyat. Hidup dan terus mewarnai semangat juang rakyat.
Begitulah, karangan bunga, taburan bunga, bahkan gundukan tanah pun dijumput para peziarah. Yang tampak keesokan harinya, 23 Juni 1970 adalah pusara berhias tanah merah. Merah menyalakan semangat tiada padam. Biarpun jazad terkubur dalam tanah, semangat tak akan lekang dimakan waktu. Biar jazad hancur menyatu dengan tanah, tapi kobaran semangat perjuangan tetap menyala. Sukarno hanya mati jazad, namun ruh dan jiwanya tetap menyatu dengan rakyat. Hidup dan terus mewarnai semangat juang rakyat.
Manusia Sukarno telah tiada. Putra Sang Fajar yang lahir tatkala surya mulai bersinar, telah kembali dalam pelukan bumi Nusantara yang sangat ia cintai. Ia masuk pelukan bumi ketika matahari condong ke barat, menuju peraduan malam. Begitulah matahari bersinar dan tenggelam setiap hari. Begitulah manusia lahir dan mati. Namun bagi bangsa Indonesia, nama Bung Karno akan tetap dikenang, diingat karena perjuangannya, pengabdiannya, dan pengorbanannya yang dengan sepenuh hati telah ia baktikan.
Terima kasih, ya Tuhan, Engkau telah memberi kami seorang manusia Sukarno yang telah lahir dalam permulaan abad ke-20, dan membebaskan bangsa ini dari penjajah. (roso daras)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar